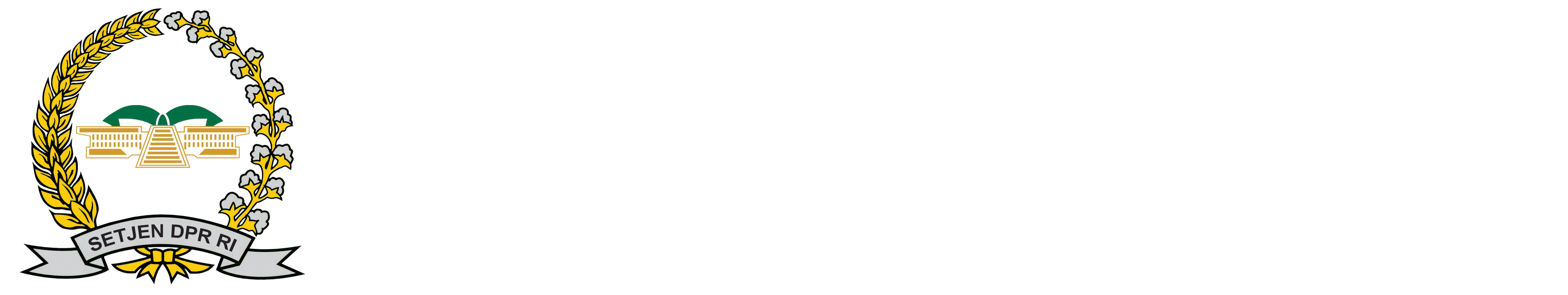
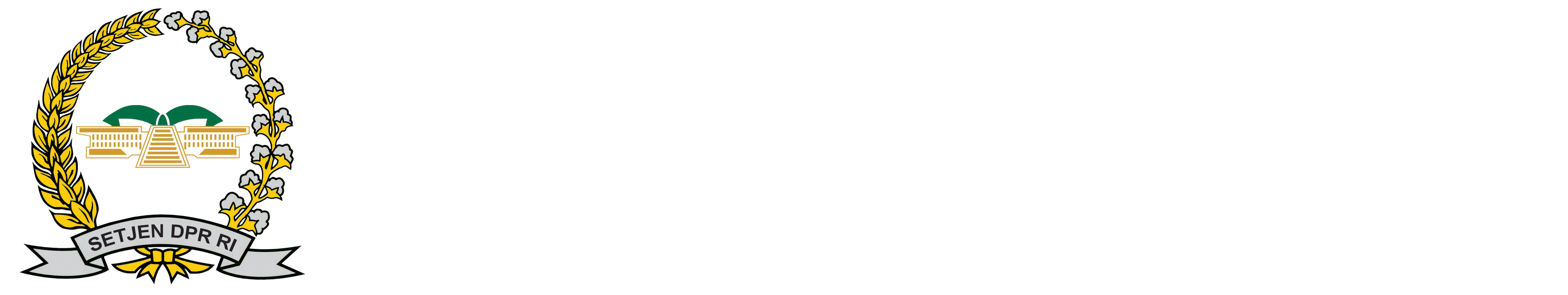

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Aisyah Sharifa
Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP, serta Pasal 4 UU Pencegahan
Penodaan Agama
Pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945
Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 76/PUU-XVI/2018
perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.
Bahwa terhadap pengujian Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP, serta
Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama dalam permohonan a quo,
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 156 dan
Pasal 157 ayat (1) KUHP serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama
seolah-olah menutup mata adanya perbedaan dalam beragama di
Indonesia dan menderogasi hakikat agama, beribadah, dan toleransi dan
karenanya bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Menurut
Mahkamah, sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan-putusan
Mahkamah sebelumnya, Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia
tidak memberikan kemungkinan adanya kampanye kebebasan untuk tidak
beragama, kebebasan untuk promosi anti agama serta tidak
memungkinkan untuk menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-
kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama
Tuhan. Sebaliknya Konstitusi memberikan jaminan terkait dengan
kebebasan beragama warga negaranya. Kebebasan beragama merupakan
salah satu hak asasi manusia yang sangat fundamental, melekat dalam
diri setiap manusia. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah
Nomor 140/PUU-VII/2009, Paragraf [3.55] menyatakan:
…bahwa beragama dalam pengertian meyakini suatu agama tertentu
merupakan ranah forum internum, merupakan kebebasan, merupakan
hak asasi manusia yang perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah
[vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. Negara dalam melaksanakan
tanggung jawabnya untuk menegakkan dan melindungi hak asasi
manusia sesuai dengan prinsip negara hukum, maka pelaksanaan hak
asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945];
Bahwa beragama dalam pengertian melaksanakan atau mengamalkan
keyakinan merupakan ranah forum externum yang terkait dengan hak
asasi manusia orang lain, terkait dengan kehidupan kemasyarakatan,
dengan kepentingan publik, dan dengan kepentingan negara…
Berdasarkan pertimbangan tersebut, kebebasan untuk meyakini
kepercayaan adalah kebebasan yang tidak dapat dibatasi dengan
pemaksaan bahkan tidak dapat diadili, karena kebebasan demikian adalah
kebebasan yang ada dalam pikiran dan hati seseorang yang meyakini
kepercayaan itu (forum internum). Akan tetapi jika kebebasan untuk
menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (forum
externum) sudah menyangkut relasi dengan pihak lain dalam suatu
masyarakat maka kebebasan yang demikian dapat dibatasi. Pembatasan
tersebut hanya dapat dilakukan dengan undang-undang dengan maksud
semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang disesuaikan
dengan pertimbangan moral, nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban
umum dalam masyarakat yang demokratis. Lebih jauh, Mahkamah dalam
pertimbangan hukum Paragraf [3.16.5] Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 56/PUU-XV/2017, bertanggal 23 Juli 2018, menyatakan,
… Negara perlu menentukan pembatasan-pembatasan tertentu agar
pelaksanaan hak dan kebebasan beragama tidak saling berkonflik satu
dengan yang lain maupun konflik dalam satu agama tertentu. Peran
negara bukanlah dimaksudkan untuk membatasi keyakinan seseorang
(forum internum) melainkan lebih dimaksudkan pada pembatasan
terhadap ekspresi beragama melalui pernyataan dan sikap sesuai hati
nurani di muka umum (forum externum) sehingga tidak menyimpang dari
pokok-pokok ajaran agama yang dianut. Dalam konteks inilah
sesungguhnya kepastian hukum perlindungan hak dan kebebasan
beragama harus ditempatkan. Kepastian hukum atas hak dan kebebasan
beragama bukanlah semata kepastian hukum bagi hak perorangan,
melainkan juga kepastian hukum yang adil dalam kerangka hak beragama
dan berkeyakinan dalam tatanan kehidupan bersama pada satu agama
dan antar umat beragama …
Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, berkenaan dengan
beragama pada dasarnya terbagi menjadi dua. Pertama, beragama dalam
pengertian meyakini suatu agama tertentu yang merupakan ranah forum
internum yang tidak dapat dibatasi dengan pemaksaan bahkan tidak
dapat diadili. Kedua, beragama dalam pengertian melaksanakan atau
mengamalkan keyakinan yang merupakan ranah forum externum.
Beragama dalam pengertian kedua inilah yang dapat dibatasi
pelaksanaannya oleh negara melalui undang-undang yakni apabila dalam
pelaksanaannya terkait dengan hak asasi manusia orang lain, terkait
dengan kehidupan kemasyarakatan, dengan kepentingan publik, dan
dengan kepentingan negara. Dengan kata lain, pembatasan sebagaimana
diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP serta Pasal 4 UU
Pencegahan Penodaan Agama adalah pembatasan yang terkait dengan
beragama dalam pengertian melaksanakan atau mengamalkan keyakinan
(forum externum) dan karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 29
ayat (2) UUD 1945. Sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan
bahwa pasal-pasal a quo seolah-olah menutup mata adanya perbedaan
dalam beragama di Indonesia dan menderogasi hakikat agama,
beribadah, dan toleransi adalah tidak beralasan menurut hukum.
[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 156 dan
Pasal 157 ayat (1) KUHP serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama
tidak memiliki tujuan yang tepat dalam paradigma pemidanaan, baik
retributif maupun utilitarian, dan justru menghalangi ibadah yang sejati
umat beragama yakni untuk memberitakan kebenaran agama baik
kepada mereka yang berbeda agama maupun kepada penista agama.
Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, keberadaan UU Pencegahan
Penodaan Agama dapat dijadikan dasar untuk mencegah tindakan
penyalahgunaan agama dan penodaan terhadap agama melalui tindakan
administratif yang paling ringan sampai dengan tindakan administratif
yang paling berat. Jika dengan penjatuhan sanksi administratif ternyata
tidak dapat mengubah sikap dan perilakunya yang menimbulkan
keresahan masyarakat maka pengenaan sanksi pidana dapat dilakukan
sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Pemidanaan terhadap
penyalahgunaan agama dan penodaan/penistaan agama adalah penting
karena dalam bentuk apapun, baik dilakukan perorangan maupun
kelompok, penodaan dan penyalahgunaan agama adalah tindakan yang
tidak dapat dibenarkan dalam pandangan hukum. Hal ini dikarenakan
tidak ada orang atau lembaga manapun yang berhak melecehkan agama
dan memperlakukan tidak hormat unsur-unsur keagamaan lain yang pada
akhirnya menimbulkan keresahan dan kemarahan publik [vide Putusan
Mahkamah Nomor 140/PUU-VII/2009].
Penggunaan norma hukum administratif dan/atau norma hukum
pidana dalam UU Pencegahan Penodaan Agama dan KUHP tersebut
tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Justru dengan adanya kedua
norma tersebut menguatkan berlakunya hak asasi manusia, khususnya
yang mengatur kebebasan berpikir dan berpendapat, agar penggunaan
kebebasan berpikir atau berpendapat tersebut tidak malah justru
menjauhkan seseorang dari ketaatan terhadap agama yang diyakininya,
melainkan dapat meningkatkan kualitas dirinya di hadapan Tuhan dan
ajaran-ajaran-Nya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut dalil para Pemohon yang menyatakan
Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP serta Pasal 4 UU Pencegahan
Penodaan Agama tidak memiliki tujuan yang tepat dalam paradigma
pemidanaan, baik retributif maupun utilitarian, dan justru menghalangi
ibadah yang sejati umat beragama yakni untuk memberitakan kebenaran
agama baik kepada mereka yang berbeda agama maupun kepada penista
agama adalah tidak beralasan menurut hukum.
[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang
menyatakan pasal-pasal a quo membuat orang dengan mudahnya
menuduh orang lain melakukan penistaan agama, menurut Mahkamah,
pasal-pasal a quo justru merupakan ketentuan yang bertujuan untuk
menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kalangan masyarakat agar
jangan sampai terkena berbagai macam hasutan yang mengacau dan
memecah belah dengan jalan berpidato, tulisan, gambar, dan lain
sebaginya di depan umum atau di media massa. Andaipun dalil para
Pemohon tersebut benar adanya, quod non, hal tersebut bukanlah
permasalahan konstitusionalitas melainkan terkait dengan penerapan
norma yang harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang- undangan yang berlaku. Ihwal kekhawatiran para
Pemohon bahwa orang dengan mudahnya menuduh orang lain
melakukan penistaan agama, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 56/PUU-XV/2017, telah menegaskan antara lain:
Terhadap kekhawatiran dan penilaian demikian Mahkamah hendak
menegaskan kembali bahwa negara harus menjamin perlindungan bagi
setiap warga negara yang hendak melaksanakan hak konstitusionalnya
secara damai, termasuk dalam menganut agama dan keyakinan, dengan
tidak membiarkan adanya tindakan main hakim sendiri atau persekusi.
Selanjutnya dalam kaitannya dengan kewajiban negara untuk melindungi
hak konstitusional setiap warga negara atas kebebasan beragama dan
berkeyakinan, dalam putusan tersebut telah ditegaskan:
bahwa belum dilakukannya revisi atas UU 1/PNPS/1965 sama sekali tidak
mengurangi kewajiban negara untuk melindungi hak atas kebebasan
beragama dan berkeyakinan setiap warga negara. Artinya, dengan
adanya peristiwa-peristiwa main hakim sendiri atau persekusi
sebagaimana diuraikan di atas, revisi terhadap UU 1/PNPS/1965 semakin
mendesak untuk dilakukan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 140/PUU-VII/2009.
[3.18] Menimbang bahwa terhadap petitum para Pemohon yang
meminta bahwa frasa “golongan” dalam Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1)
KUHP dimaknai tidak termasuk golongan berdasarkan agama, Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut:
[3.18.1] Bahwa Pasal 156 KUHP adalah ketentuan mengenai ancaman
pidana yang dapat dikenakan kepada seseorang yang menyatakan
perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau
beberapa golongan rakyat Indonesia di muka umum. Adapun Pasal 157
ayat (1) KUHP adalah ketentuan mengenai ancaman pidana yang dapat
dikenakan kepada seseorang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau
menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang isinya
mengandung pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan di
antara atau terhadap golongan rakyat Indonesia, dengan maksud isinya
diketahui atau lebih diketahui oleh umum. Kedua ketentuan tersebut pada
pokoknya menekankan pada perbuatan yang mengandung pernyataan
permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa
golongan rakyat Indonesia. Pengertian golongan sebagaimana tertuang
dalam Pasal 156 KUHP adalah tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang
berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri
asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan
menurut hukum tata negara. Pengertian golongan ini berlaku bukan
hanya untuk Pasal 156 KUHP namun juga terhadap pasal-pasal
selanjutnya.
Adalah benar bahwa KUHP Indonesia merupakan adopsi dari KUHP
Belanda yang pada saat itu diberlakukan di Indonesia, namun pasal
tersebut tidak ada padanannya dalam KUHP Belanda karena di Belanda
pada saat itu semua pada umumnya sama (homogen), baik suku bangsa,
adat istiadat, bahasa, maupun agama. Berkebalikan dengan
Belanda,Indonesia memiliki keragaman dalam berbagai hal, antara lain,
suku bangsa, adat istiadat, dan agama, yang merupakan keniscayaan
yang harus dilindungi. Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP merupakan
ketentuan yang bertujuan untuk mencegah gejolak sosial yang berbau
SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).
[3.18.2] Bahwa terkait frasa “golongan”, Mahkamah telah menafsirkan
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017, bertanggal
28 Maret 2018 perihal Pengujian Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2)
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Putusan
tersebut, frasa “golongan” meliputi/mencakup suku, agama, dan ras.
Adapun istilah “antargolongan” tidak hanya meliputi suku, agama, dan
ras, melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak
terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras. Dengan
demikian, memberikan makna bahwa frasa “golongan” tidak termasuk
golongan berdasarkan agama sebagaimana petitum permohonan para
Pemohon, selain meniadakan/menghilangkan perlindungan hukum bagi
agama itu sendiri yang berarti pelanggaran terhadap UUD 1945 juga
bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-
XV/2017.
[3.18.3] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada Paragraf
[3.18.1] dan Paragraf [3.18.2] di atas, menurut Mahkamah, dalil
permohonan para Pemohon mengenai frasa “golongan” dalam Pasal 156
dan Pasal 157 ayat (1) KUHP yang dimaknai tidak termasuk golongan
berdasarkan agama adalah tidak beralasan menurut hukum.
[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan
hukum di atas, Mahkamah berpendapat pemohonan para Pemohon
mengenai inkonstitusionalitas Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP
serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak beralasan menurut
hukum.
Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430