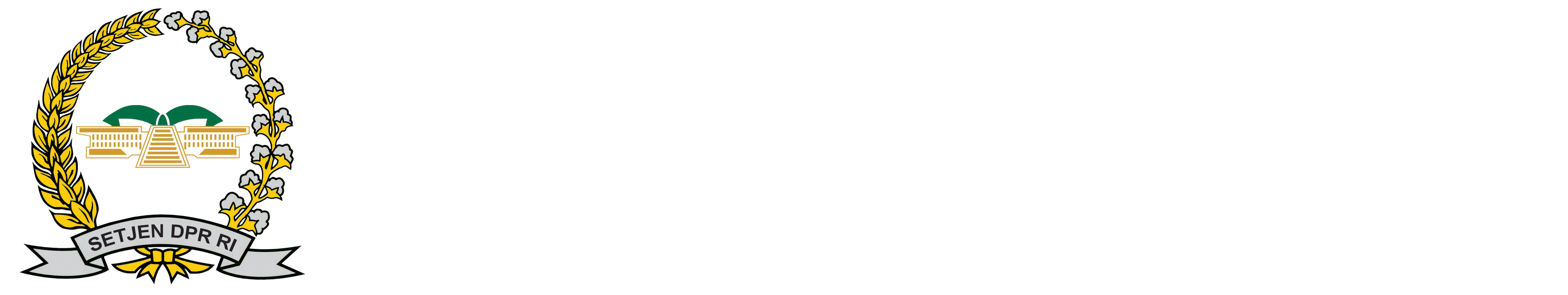
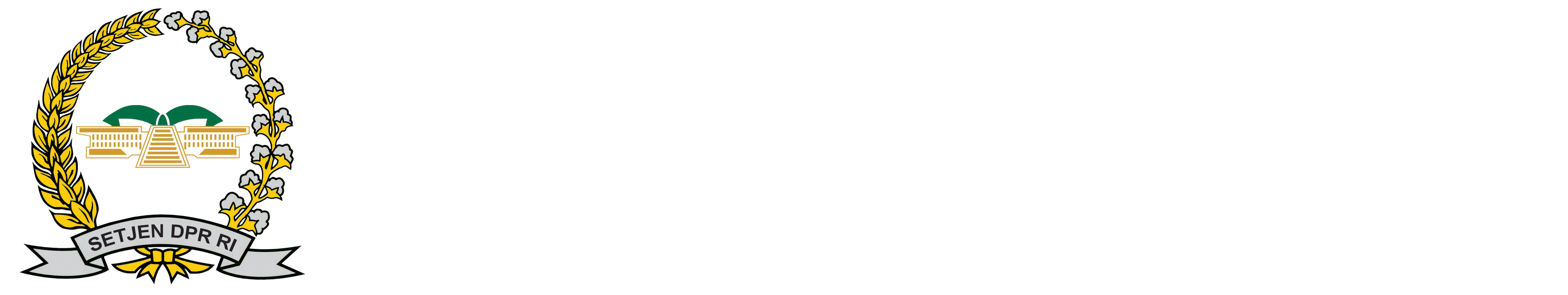

Mahmudi (Sekretaris Desa), selanjutnya disebut sebagai Pemohon
Pasal 51 huruf g UU Desa
Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.
Bahwa terhadap pengujian Pasal 51 huruf g UU Desa dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan a quo, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi pokok yang didalilkan oleh Pemohon, telah ternyata yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 51 huruf g UU 6/2014 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 karena tidak memberikan kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul melalui partisipasi dalam organisasi partai politik serta tidak memberikan hak untuk memajukan diri sebagai pengurus partai politik untuk mewujudkan tujuan partai politik sebagaimana dimaksud dalam UU Parpol. Terhadap dalil Pemohon a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permasalahan tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
[3.10.1] Bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang artinya hukum sebagai pedoman bernegara dan bermasyarakat. Kekuasaan negara dan organ negara berdasarkan pada konstitusi dan hukum serta menolak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang (arbitrary power). Supremasi hukum, asas persamaan perlakuan di muka hukum dan pemerintahan (equality before the law), dan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi merupakan prinsip yang menjadi unsur penting setiap negara hukum. Hak asasi manusia merupakan unsur utama yang harus dilindungi dan dikembangkan dalam negara hukum. Negara dalam hal ini harus mampu memberikan jaminan, perlindungan, dan pengembangan hak asasi manusia dalam suatu masyarakat yang demokratis.
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul merupakan hak dasar dalam negara hukum dan demokratis yang berkedaulatan rakyat serta dijamin dalam konstitusi yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Secara konstitusional, Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Lebih lanjut, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Dengan demikian, UUD 1945 secara tegas telah memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat (freedom of association), kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan kebebasan menyatakan pendapat (freedom of expression) bagi setiap orang. Secara internasional pun, Pasal 20 Universal Declaration of Human Rights dan Pasal 21 Covenant on Civil and Political Rights telah memberikan jaminan bagi setiap orang untuk memiliki hak bebas dan merdeka dalam berserikat dan berkumpul.
Jika dikaitkan dengan realisasi dari pemikiran filosofis, kemerdekaan berserikat dan berkumpul pada hakikatnya merupakan hak dasar bahwa manusia sejatinya bebas dan tidak dikekang. Ketika orang melakukan kegiatan berkumpul untuk melaksanakan kegiatan berserikat tentunya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Penyampaian pikiran di muka umum merupakan unsur adanya partisipasi politik masyarakat yang dapat diterjemahkan sebagai dukungan terbuka terhadap kepentingan politik tertentu. Dengan demikian, kemerdekaan berserikat dan berkumpul merupakan bentuk pengejawantahan kedaulatan rakyat demokrasi dalam pelaksanaan hak asasi manusia di negara hukum.
Penjabaran dari amanat konstitusi terkait hak untuk berserikat dan berkumpul kemudian diwujudkan salah satunya dalam pembentukan partai politik yang merupakan bagian dari pilar demokratis dalam sistem politik Indonesia [vide Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011)]. Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai salah satu lembaga demokrasi, partai politik berfungsi mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat, menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara, serta membina dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. Dengan demikian, diperlukan jaminan dari negara bagi setiap warga negara untuk memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan negara melalui partai politik.
[3.10.2] Bahwa secara konstitusional dalam pelaksanaannya hak asasi manusia boleh dibatasi, namun pembatasan ini hanya dapat dilakukan dengan alasan tertentu dan memenuhi kaidah tertentu juga. Ketentuan Pasal 28J UUD 1945 telah memberikan legitimasi kepada negara melalui pembentuk undang-undang untuk melakukan pembatasan terhadap penggunaan hak dan kebebasan setiap orang dalam undang-undang. Pembatasan ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin serta menghormati hak dan kebebasan orang lain, dan demi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Terdapat suatu kecenderungan yang sama dari negara hukum yang demokratis terkait dengan pembatasan terhadap hak asasi manusia yaitu bahwa pembatasan terhadap hak tersebut tidak hanya berlaku dalam keadaan darurat tetapi juga dalam keadaan normal, seperti untuk memelihara ketertiban umum, melindungi kepentingan negara dan/atau pemerintahan, mencegah kemerosotan moral masyarakat atau publik, mencegah timbulnya dorongan melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum dan lain sebagainya.
Secara doktriner terdapat dua rasionalitas mengapa diperlukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) yaitu pertama, pembatasan hak asasi didasarkan pada adanya pengakuan bahwa sebagian besar HAM tidak bersifat mutlak, melainkan mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individual dan kepentingan umum. Kedua, untuk mengatasi konflik antar hak, misalnya hak berekspresi yang harus dibatasi karena adanya penghormatan atas hak privasi seseorang, sehingga hak yang satu dapat dibatasi demi memberikan ruang bagi terlaksananya hak lainnya. Beberapa hak secara internasional telah disepakati menjadi hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun bahkan dalam keadaan darurat perang sekalipun. Hak-hak tersebut dikenal dengan non derogable rights yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Covenant on Civil and Political Rights. Adapun non derogable rights tersebut meliputi hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak tidak diperbudak, hak untuk tidak dipenjara karena semata-mata tidak dapat memenuhi kewajiban kontraknya, hak untuk tidak dihukum berdasarkan hukum yang berlaku surut, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, hak atas bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama. Dalam konstitusi berkaitan dengan non derogable rights telah diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Meskipun demikian, norma Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tersebut haruslah dibaca bersama-sama dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 [vide Putusan Mahkamah Konstitusi di antaranya Nomor 065/PUU-II/2004, Nomor 2-3/PUU-V/2007].
Bahwa berkenaan dengan adanya larangan terhadap kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa untuk merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik sebagaimana diatur dalam UU 6/2014, ketentuan tersebut merupakan ketentuan khusus yang melekat sebagai perlindungan terhadap pengaturan pokok dalam UU 6/2014 (lex specialis). Sedangkan, pengaturan mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul dalam UU 2/2011 yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia melalui wadah partai politik merupakan pengaturan yang bersifat umum (lex generalis) karena berlaku bagi setiap orang sepanjang telah memenuhi persyaratan tertentu dan tanpa membedakan jabatan serta kedudukan sosialnya. Sesuai dengan asas dalam hukum yang menyatakan lex specialis derogate legi generalis, yaitu ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum, sehingga pembatasan/larangan bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa untuk menjadi pengurus partai politik bukan merupakan perlakuan diskriminasi dan sewenang-wenang terhadap jabatan tersebut.
[3.11] Menimbang bahwa setelah menegaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan masalah konstitusionalitas norma Pasal 51 huruf g UU 6/2014 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yaitu apakah ketentuan norma a quo melanggar kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan bagi perangkat desa sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut:
[3.11.1] Bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia [vide Pasal 1 angka 2 UU 6/2014]. Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan desa mempunyai kekuasaan tertinggi di tingkat desa dan berperan penting terhadap jalannya pemerintahan desa menuju kesejahteraan masyarakat. Kepala desa merupakan jabatan yang sangat dihormati di kalangan masyarakat desa karena selain sebagai pemimpin desa, kepala desa juga merupakan elite lokal yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat desa. Oleh karena itu, kepala desa merupakan jabatan strategis sebagai penggerak politik masyarakat.
Keberadaan perangkat desa yang juga diserahi tugas di bidang administrasi termasuk memiliki posisi penting sebagai aparatur pemerintahan yang paling bawah. Perangkat desa merupakan salah satu organ pemerintah desa selain kepala desa yang kedudukannya berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU 6/2014 merupakan pembantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa. Meskipun kedudukannya sebagai pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, namun UU 6/2014 telah menempatkan perangkat desa di posisi yang sangat penting dalam pemerintahan desa karena selain menyandang atribut dan simbol-simbol yang diberikan negara, perangkat desa juga menjalankan tugas-tugas negara. Meskipun pengangkatan perangkat desa sangat tergantung kepada kepala desa sebagai pihak yang berkepentingan langsung, namun kewenangan yang melekat pada jabatan ini diatur sedemikian rupa agar personal yang terpilih sebagai perangkat desa benar-benar mampu menjalankan tugasnya. Selain itu, baik pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa harus dikonsultasikan oleh kepala desa kepada Camat atas nama Bupati/Walikota untuk memperoleh rekomendasi [vide Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (3) UU 6/2014].
Sebagai pembantu kepala desa, perangkat desa akan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dari kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU 6/2014 misalnya, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa juga menetapkan peraturan desa. Sebagai bagian dari lembaga pemerintahan di kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat, baik kepala desa maupun perangkat desa akan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, sesungguhnya kedudukan perangkat desa sangat strategis sehingga diharapkan dapat diisi oleh orang-orang yang bukan saja profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, namun juga merupakan pribadi yang dapat diterima, dipercaya dan dihormati sebagai pamong desa, serta memperoleh legitimasi dari masyarakat desa dalam menjalankan pemerintahan desa untuk membawa masyarakat desa ke arah terwujudnya kesejahteraan, ketertiban, dan kemajuan desa. Oleh karena itu, dalam membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut dibutuhkan adanya independensi, profesionalitas, dan ketidakberpihakan (netralitas) dari perangkat desa khususnya dalam memberikan pelayanan publik.
[3.11.2] Bahwa netralitas merupakan asas yang sangat penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan yang diemban setiap pegawai pemerintah, maupun pejabat pemerintah atau pejabat negara agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan dan sikap netral, dalam arti tidak memihak atau bebas, maksudnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus bebas dari kepentingan, intervensi, bebas dari pengaruh, adil, objektif, dan tidak memihak. Adapun netralitas politik dimaksudkan tidak terlibat dan tidak memihak terhadap kepentingan partai politik tertentu. Dalam upaya menjaga netralitas jabatan, baik kepala desa dan perangkat desa harus lepas dari pengaruh partai politik dalam rangka menjamin persatuan dan kesatuan serta menjamin keberlangsungan pelayanan publik tetap terselenggara dengan baik melalui pemusatan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepada mereka.
Berkenaan dengan hal di atas, sebagai konsekuensi dari kewenangan yang melekat pada jabatan perangkat desa sebagai pembantu kepala desa, sudah seharusnya terdapat pengaturan terhadap netralitas politik yaitu berupa larangan untuk menjadi pengurus partai politik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 huruf g UU 6/2014. Keterlibatan perangkat desa dalam kepengurusan suatu partai politik akan menyebabkan munculnya berbagai permasalahan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa. Besarnya kemungkinan terjadi keberpihakan dari perangkat desa terhadap partai politik yang dinaunginya kemudian dapat dimanifestasikan dalam pembentukan kebijakan dan penggunaan anggaran desa. Hal demikian sangat berpotensi menimbulkan kecemburuan yang menyebabkan perpecahan antar perangkat desa sehingga pada akhirnya akan berdampak pada pengabaian terhadap kepentingan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.
Bahwa dalam menjalankan pemerintahan desa dibutuhkan pemangku jabatan yang netral serta bebas dari pengaruh kepentingan politik tertentu sehingga harus diatur tersendiri adanya pembatasan keterlibatan politik bagi kepala desa maupun perangkat desa sebatas keterlibatan dalam menjadi pengurus suatu partai politik agar dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap memusatkan perhatian kepada pelayanan publik demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal demikian tidak dapat diartikan sebagai bentuk penghilangan kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam suatu wadah partai politik bagi kepala desa, perangkat desa, maupun anggota badan permusyawaratan desa, namun pembatasan tersebut dikarenakan terdapatnya kepentingan publik yang lebih besar dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, pembatasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena baik kepala desa, perangkat desa maupun anggota badan permusyawaratan desa masih dapat menggunakan hak politiknya untuk memberikan suaranya dalam pemilu. Di samping itu, secara normatif sesuai dengan asas hukum, UU 6/2014 merupakan lex specialis sedangkan UU Parpol merupakan lex generalis. Oleh karena itu, ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum (lex specialis derogate legi generalis), sehingga adanya pembatasan/larangan bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa menjadi pengurus partai politik bukan merupakan perlakuan diskriminasi terhadap jabatan tersebut.
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan telah terjadi pelanggaran terhadap kemerdekaan berserikat dan berkumpul karena dilarangnya perangkat desa menjadi pengurus partai politik sebagaimana terdapat dalam ketentuan norma Pasal 51 huruf g UU 6/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum.
[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 51 huruf g UU 6/2014 telah ternyata memberikan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta memberikan hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430