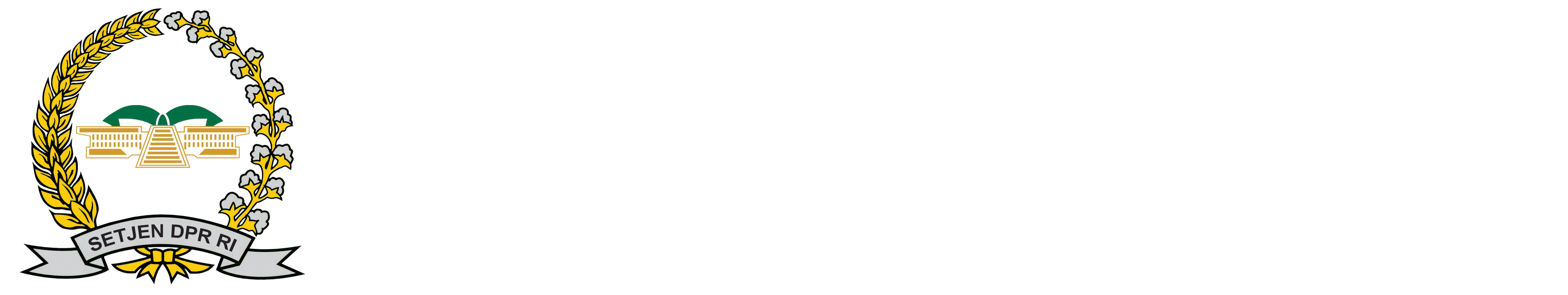
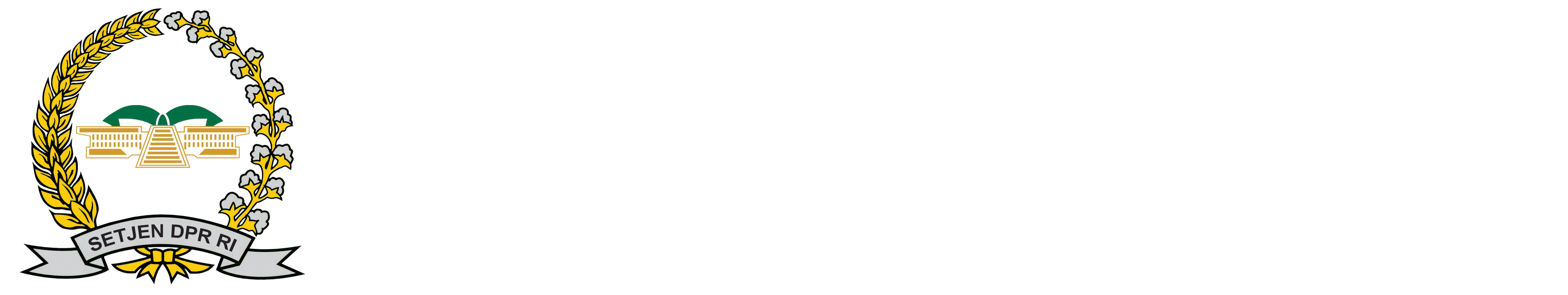

Marzuki Darusman, Muhammad Busyro Muqoddas, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang memberikan kuasa kepada Usman Hamid, S.H., M.Phil, dkk, kuasa hukum dan/atau advokat yang tergabung dalam Tim Universitas Hak Asasi Manusia (U-HAM), untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.
Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU 26/2000
Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.
Bahwa terhadap pengujian ketentuan UU 26/2000 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
[3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil pokok permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
[3.14.1] Bahwa perkembangan pengaturan mengenai HAM dalam konstitusi di Indonesia mengalami dinamika sejak pembahasan rancangan undang-undang dasar dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tahun 1945, jauh sebelum adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948. Kesepakatan yang diambil pada akhirnya menerima hak warga negara untuk dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar secara terbatas dan akan diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Selain itu, konsep yang digunakan adalah “hak warga negara” (citizen rights) bukan “hak asasi manusia” (individual human rights). Penggunaan konsep “hak warga negara” tersebut berarti secara implisit tidak diakui paham natural rights yang menyatakan HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia oleh karena ia lahir sebagai manusia. Selanjutnya, pada saat berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 di dalamnya memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum perubahan. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh berlakunya DUHAM pada tanggal 10 Desember 1948. Oleh karenanya, Konstitusi RIS 1949 mengatur tentang HAM dalam Bagian V sebanyak 27 pasal, sedangkan UUDS 1950 juga mengaturnya dalam Bagian V yang terdiri atas 28 pasal. Diskursus mengenai HAM muncul kembali pada sidang konstituante, khususnya dari Komisi Hak Asasi Manusia, yang relatif lebih menerima HAM dalam pengertian natural rights dan menyepakati 24 jenis HAM yang nantinya akan disusun dalam satu Bab di konstitusi yang baru. Namun, ketika konstituante belum berhasil menyepakati konstitusi baru, berdasarkan Keppres Nomor 150 Tahun 1959 bertanggal 5 Juli 1959 (Dekrit Presiden), Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan menyatakan UUD 1945 berlaku kembali. Dengan pemberlakuan tersebut, ketentuan tentang hak warga negara yang tercantum dalam UUD 1945 pun berlaku kembali. Perubahan signifikan mengenai pengaturan HAM dalam konstitusi baru terjadi seiring dengan tuntutan reformasi dan perubahan UUD 1945. Dalam perubahan UUD 1945 tahun 1999-2000, dihasilkan Bab khusus yang mengatur mengenai HAM yang memperluas Pasal 28 UUD 1945 yang semula hanya terdiri atas satu pasal dan satu ayat, menjadi beberapa pasal dan ayat, mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945.
[3.14.2] Bahwa secara kategoris, jaminan HAM dalam UUD 1945 hasil perubahan mencakup hak sosial-politik, hak kultural dan ekonomi, hak kolektif, hak atas lingkungan hidup, hak atas pembangunan dan lain sebagainya yang tersebar dalam sejumlah pasal, tidak terbatas pada pengaturan dalam BAB XA tentang HAM. Pada umumnya, perumusan hak dalam UUD 1945 dirumuskan dengan menggunakan frasa “setiap orang berhak” (individual human rights) dan hanya beberapa hak yang dirumuskan sebagai hak warga negara, misalnya tentang kesempatan yang sama dalam pemerintahan [vide Pasal 28D ayat (3) UUD 1945], hak dalam usaha pertahanan dan keamanan negara [vide Pasal 30 ayat (1) UUD 1945], dan hak memperoleh pendidikan [vide Pasal 31 ayat (1) UUD 1945]. Perbedaan perumusan tersebut memiliki konsekuensi dalam implementasinya. Perumusan hak konstitusional sebagai individual human rights dapat memberikan peluang untuk dijamin dan ditegakkan dalam konteks prinsip universalitas HAM, tidak seperti pemenuhan hak warga negara yang hanya terbatas bagi warga negara yang bersangkutan (bukan sebagai hak semua orang). Namun demikian, meskipun dirumuskan sebagai individual human rights, menurut Mahkamah, pelaksanaan hak tersebut sangat terkait dengan hubungan konstitusional (constitutional and political relations) antara pemegang hak dengan konstitusi dan negara. Artinya, pelaksanaan HAM yang telah dirumuskan dalam konstitusi secara kontekstual sangat berkaitan dengan yurisdiksi suatu negara. Menurut Mahkamah, terkait dengan politik hukum HAM di Indonesia, tidak hanya sekadar berpijak pada prinsip universalisme HAM, namun tetap menjaga keberlakuan sosial-budaya berdasarkan prinsip partikularisme yang tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan dan pemenuhan HAM tetap harus diletakkan dalam koridor perlindungan terhadap kepentingan nasional tiap negara sebagaimana telah ditentukan dalam konstitusi masing-masing negara. Dengan demikian, meskipun rumusan HAM dalam UUD 1945 memuat frasa “setiap orang”, maka tidak secara otomatis menimbulkan tanggung jawab aktif bagi negara (pemerintah) Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia tiap individu yang bukan warga negaranya.
[3.14.3] Bahwa terkait dengan digunakannya frasa “setiap orang” pada rumusan mengenai hak-hak konstitusional dalam Bab XA UUD 1945 yang tidak mengenal adanya pembedaan antara hak asasi seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing, sangat mungkin menimbulkan kesalahpahaman apabila dilepaskan dari konteks perlindungan dan penegakan HAM yang menjadi tanggung jawab suatu negara. Karena, hal demikian secara otomatis dapat diartikan memberikan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk berperan secara aktif dalam memberikan perlindungan kepada warga negara asing. Meskipun perumusan frasa “setiap orang” dalam UUD 1945 dapat diartikan hak asasi tidak hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia, tetapi juga termasuk warga negara asing yang dijamin dan dilindungi oleh sistem hukum dan peradilan Indonesia, namun tidak berarti dalam sistem hukum Indonesia berlaku secara otomatis bahwa setiap orang harus diperlakukan dan mendapatkan hak yang sama tanpa mempertimbangkan status kewarganegaraannya. Sebagai contoh, adanya perjanjian internasional antar negara yang bersifat bilateral yang mengatur tentang perlindungan terhadap warga negara dari negara lain membuktikan bahwa terdapat adanya pembedaan hak antara warga negara sendiri dengan warga negara asing tergantung pada yurisdiksi masing-masing negara. Oleh sebab itu, bukanlah merupakan hal yang dilarang apabila dalam praktik pelaksanaan atau pemenuhan HAM dapat terhalang oleh ketentuan prosedural hukum acara yang hanya memberi akses peradilan nasional kepada warga negaranya, sepanjang hal tersebut telah ditetapkan dalam hukum positif di negara tersebut.
[3.14.4] Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan isu mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar tidak dapat dilepaskan pula dari isu politik. Dalam kaitan ini, Indonesia telah memiliki komitmen sebagai bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang tetap harus berpedoman pada prinsip hubungan luar negeri dan politik luar negeri yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, yaitu prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU 37/1999) telah memberikan pengertian yang dimaksud dengan "bebas aktif" adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia. Selain itu, juga secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sementara yang dimaksud dengan diabdikan untuk kepentingan nasional adalah politik luar negeri yang dilakukan guna mendukung terwujudnya tujuan nasional sebagaimana dimaktubkan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Pengertian “bebas aktif” a quo juga sebangun dengan pandangan Soekarno yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul “Di Bawah Bendera Revolusi” sebagai berikut:
“... Sebab kita tidak netral, kita tidak penonton-kosong daripada kejadian-kejadian di dunia ini, kita tidak tanpa prinsip, kita tidak tanpa pendirian. Kita menjalankan politik bebas itu tidak sekadar secara ”cuci tangan”, tidak sekadar secara defensif, tidak sekadar secara apologetis. Kita aktif, kita berprinsip, kita berpendirian! Prinsip kita ialah terang Pancasila, pendirian kita ialah aktif menuju kepada perdamaian dan kesejahteraan dunia, aktif menuju kepada persahabatan segala bangsa, aktif menuju kepada lenyapnya exploitation de l’homme par l’homme, aktif menentang dan menghantam segala macam imperialisme dan kolonialisme di mana pun ia berada,"
Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran yang sangat strategis untuk menentukan langkah kebijakan yang akan ditempuh dalam relasi internasional dengan negara lain, termasuk juga yang berkaitan dengan isu penegakan HAM. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan risiko atau dampak yang akan timbul sebagai ekses dari kebijakan politik luar negeri yang diambil, baik dari aspek hukum, politik, sosial maupun ekonomi. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konsepsi ketahanan nasional dalam rangka mewujudkan daya tangkal dan daya tahan untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia [vide Penjelasan Pasal 2 UU 37/1999]. Menurut Mahkamah, konsep ketahanan nasional dimaksud setidaknya dapat dioperasionalkan dalam bentuk: (i) ketahanan yang menyangkut wilayah, warga negara, dan sistem politik termasuk di dalamnya politik global yang sedang terjadi; (ii) ketahanan ekonomi yang menyangkut kerja sama antarnegara dalam ekonomi global yang berdampak positif bagi negaranya; serta (iii) ketahanan ideologi yang berkaitan dengan cara negara untuk menjaga Pancasila dari ancaman ideologi negara lain.
[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah selanjutnya akan menilai konstitusionalitas norma frasa “oleh warga negara Indonesia” dalam Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU 26/2000 yang menurut dalil para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945. Para Pemohon memohon agar frasa “oleh warga negara Indonesia” dalam norma Pasal 5 UU 26/2000 dinyatakan inkonstitusional agar dapat diberlakukan yurisdiksi universal di Indonesia. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana Pembukaan UUD 1945. Menurut para Pemohon, hal demikian bertujuan agar para pelaku pelanggaran HAM dari negara mana pun yang memasuki teritorial Indonesia dapat diancam dan diadili oleh Pengadilan HAM Indonesia, termasuk dalam hal ini kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Myanmar. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
[3.15.1] Bahwa dalam kaitan dengan dalil para Pemohon a quo penting bagi Mahkamah menegaskan latar belakang pembentukan UU 26/2000 yang tidak dapat dilepaskan dari “peran” masyarakat internasional kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengadili para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Timor Timur. Pendirian pengadilan HAM ini merupakan salah satu bentuk usaha Indonesia untuk memenuhi kewajiban internasionalnya dengan memaksimalkan mekanisme hukum nasional dalam menangani pelanggaran HAM di dalam negerinya (exhaustion of local remedies). Hal demikian ditujukan agar mencegah masuknya mekanisme hukum internasional untuk mengadili warga negara Indonesia yang diduga melakukan pelanggaran HAM yang berat karena dalam hukum internasional, pengadilan internasional tidak dapat secara serta merta menggantikan peran pengadilan nasional tanpa melewati peran pengadilan nasional suatu negara. Jika Pengadilan HAM pada saat itu tidak dibentuk, telah terdapat upaya Internasional untuk mendorong dibentuknya International Criminal Tribunal for East Timor (ICTET) yang akan mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat, seperti pembunuhan massal, penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan berbasis gender, pemindahan penduduk secara paksa dan pembumihangusan yang terjadi di Timor Timur pasca jajak pendapat tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh militer Indonesia. Bahkan sebelumnya, melalui resolusi komisi tinggi PBB tahun 1999 dibentuk International Commission of Inquiry on East Timor (ICIET), untuk melakukan penyelidika atas kemungkinan adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum humaniter internasional di Timor Timur. Dalam kaitan ini, laporan ICIET memperlihatkan (i) adanya bukti-bukti pelanggaran atas hak-hak asasi dan hukum humaniter internasional dan merekomendasikan perlunya dibentuk mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban pelaku dan (ii) merekomendasikan dibentuknya tribunal di tingkat internasional. Kedua hal tersebut kemudian sangat mempengaruhi diterbitkannya Resolusi Nomor 1264 Tahun 1999 oleh Dewan Keamanan PBB yang isinya mengecam pelanggaran HAM yang berat di Timor Timur dan meminta para pelaku mempertanggungjawabkan tindakannya di muka pengadilan. Menyikapi resolusi tersebut dan demi melindungi kepentingan nasional yang lebih besar, maka pemerintah Indonesia menyetujui untuk dibentuk Pengadilan HAM dengan mengundangkan UU 26/2000 pada tanggal 23 November 2000 sebagai pelaksanaan dari Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) dan sekaligus menggantikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang pada saat itu tidak disetujui oleh DPR menjadi undang-undang karena dinilai masih kurang memadai [vide Konsideran Menimbang huruf c UU 26/2000].
[3.15.2] Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 5 UU 26/2000 yang pada pokoknya mengatur mengenai lingkup kewenangan (yurisdiksi) Pengadilan HAM mengandung dua hal, yaitu pelanggaran HAM yang berat, yang dilakukan oleh warga negara Indonesia (personal jurisdiction) dan di luar batas teritorial wilayah negara Indonesia (territorial jusrisdiction). Berdasarkan pencermatan secara saksama terkait dengan risalah pembahasan RUU Pengadilan HAM dan pandangan umum masing-masing fraksi serta rapat kerja Pemerintah dan Pansus RUU Pengadilan HAM dalam proses pembentukan UU 26/2000, pembahasan mengenai rumusan personal jurisdiction yang ditujukan kepada warga negara manapun (WNI dan WNA), sangatlah sumir. Pembahasan terkait personal jurisdiction untuk warga negara asing pernah disampaikan oleh I Ketut Bagiada dari Fraksi PDIP sebagaimana juga disampaikan dalam keterangan DPR yang menyatakan sebagai berikut:
“Ketika orang asing di satu wilayah negara lain melakukan pelanggaran HAM berat selain di Indonesia, kemudian kita menginginkan agar di lndonesia pun bisa dihukum masalah itu atau ditangani masalah hukum, persoalan sekarang itu bagaimana kalau kita bisa melakukan tindakan pengadilan azas resiprositas yang bersangkutan, sedangkan bukti-bukti awal di daerah atau negara lain itu persoalan yang barangkali mungkin menjadi suatu pemikiran pula agar persoalan Pelanggaran HAM di mana pun terjadi bisa ditangani secara maksimal.“
Namun, hingga berakhirnya pembahasan dan disampaikannya pendapat akhir masing-masing fraksi dalam sidang paripurna, Mahkamah tidak menemukan bukti adanya pembahasan lebih lanjut terkait hal tersebut hingga kemudian pada akhirnya UU 26/2000 disetujui dalam sidang paripurna DPR tanggal 6 November 2000. Dengan demikian, pada saat itu pembentuk undang-undang memang hanya ingin mengakomodir personal jurisdiction yang hanya ditujukan kepada warga negara Indonesia, tidak termasuk warga negara asing.
[3.16] Menimbang bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan menghilangkan frasa “oleh warga negara Indonesia” dalam norma Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU 26/2000 sebagaimana petitum para Pemohon dapat dikatakan UU 26/2000 telah menerapkan prinsip yurisdiksi universal sehingga dapat mengadili pelaku pelanggaran HAM oleh warga negara manapun. Terlebih jika pelaku pelanggaran HAM dari negara mana pun tersebut memasuki teritorial Indonesia maka dapat diancam dan diadili oleh Pengadilan HAM Indonesia, termasuk dalam hal ini kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Myanmar sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
[3.16.1] Bahwa dengan merujuk pada Prinsip 1 angka 1 dalam The Princeton Principles on Universal Jurisdiction (Princeton Principles) telah dinyatakan pengertian yurisdiksi universal merupakan kewenangan untuk mengadili suatu kejahatan yang didasarkan semata-mata pada sifat dari kejahatan tersebut, tanpa memandang di mana kejahatan tersebut dilakukan, kewarganegaraan tersangka atau pelaku yang dihukum, atau adanya hubungan lain dengan negara yang menjalankan kewenangan tersebut. Kejahatan yang dapat diberlakukan yurisdiksi universal adalah the serious crimes under international law meliputi: pembajakan, perbudakan, kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida dan penyiksaan [vide Prinsip 2 angka 1 Princeton Principles] serta terorisme [Pasal 404 Restatement (Third) of The Foreign Relations Law of United States]. Konsep yurisdiksi universal ini berpijak pada adanya anggapan bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan bagi seluruh umat manusia, dan merupakan kehendak bersama untuk menumpas kejahatan tersebut, sehingga tuntutan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap pelaku adalah atas nama seluruh masyarakat internasional.
[3.16.2] Bahwa pembahasan mengenai yurisdiksi selalu berkelindan dengan kedaulatan dan otoritas suatu negara. Dalam hal ini, setiap negara yang berdaulat pasti memiliki yurisdiksi untuk menunjukkan kewibawaan pada rakyatnya atau pada masyarakat internasional. Diakui secara universal, setiap negara memiliki otoritas mengatur tindakan-tindakan dalam wilayahnya sendiri dan tindakan lainnya yang dapat merugikan kepentingan nasional yang harus dilindungi. Dalam konteks yurisdiksi universal, maka kepentingan yang harus dilindungi adalah kepentingan masyarakat internasional dari bahaya yang ditimbulkan oleh serious crime, sehingga merasa wajib untuk menghukum pelakunya tanpa perlu adanya titik pertautan antara negara yang akan melaksanakan yurisdiksinya dengan pelaku, korban dan tempat dilakukannya kejahatan (justice beyond borders). Dalam pengertian demikian, adanya kesadaran serta kerja sama dari berbagai negara menjadi pijakan penting untuk melaksanakan yurisdiksi universal karena, jika tidak, dapat disalahartikan sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan negara lain. Dalam konteks ini, terdapat hal penting yang harus dipertimbangkan, yaitu dominannya muatan politik dalam pelaksanaan yurisdiksi universal karena terkait dengan willingness dari suatu negara untuk merelakan warga negaranya diadili oleh negara lain. Misalnya terkait dengan salah satu tujuan dari yurisdiksi universal yaitu agar suatu negara tidak memberikan tempat yang aman (no safe haven) bagi para pelaku pelanggaran HAM yang berat, juga bersifat sangat politis walaupun prosesnya melalui persidangan (hukum). Hal demikian juga akan berpengaruh terhadap hubungan diplomatik antar negara, di mana di dalamnya terdapat kerja sama ekonomi, sosial-politik, dan juga keamanan. Inilah salah satu isu hukum penting yang harus dipertimbangkan sebelum mengadopsi dan menerapkan yurisdiksi universal [vide keterangan Ahli Hikmahanto Juwana dalam persidangan tanggal 14 Maret 2023]. Dalam batas penalaran yang wajar, belum tentu suatu negara akan merelakan warga negaranya untuk diadili oleh negara lain. Kemudian adanya pembebasan dari suatu hukuman (impunity) yang diberikan kepada warga negara tertentu juga akan menghalangi proses hukum terkait dengan kebutuhan bukti-bukti dan kehadiran tersangka dalam persidangan, meskipun peradilan bisa dilaksanakan secara in absentia untuk perkara-perkara tertentu. Belum lagi dihadapkan pada tantangan terkait model hukum acara dalam melakukan penuntutan dan pemeriksaan terhadap pelaku pelanggaran HAM yang berat yang kemungkinan akan sangat berbeda perlakuan dan penerapannya antara satu negara dengan negara lain. Padahal jaminan 165 perlindungan terhadap hak-hak pelaku pelanggaran HAM yang berat yang juga harus tetap diberikan ruang dan ditegakkan dalam hukum. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu pengkajian yang komprehensif oleh pemerintah (negara), in casu pembentuk undang-undang untuk menentukan mengenai pilihan politik dan kedudukan negara Indonesia dalam tatanan masyarakat internasional serta infrastruktur hukum yang harus disediakan sebelum menerapkan yurisdiksi universal, terutama untuk memberlakukan yurisdiksi universal dalam mengadili pelanggaran HAM yang berat terhadap pelaku yang bukan warga negara Indonesia.
[3.16.3] Bahwa untuk mengakomodasi yurisdiksi universal dalam penegakan hukum terkait pelanggaran HAM yang berat, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar hukum, seperti politik, sosial budaya dan ekonomi. Oleh karenanya, dalam memperjuangkan penegakan hukum di bidang HAM Internasional tidak bisa hanya berorientasi pada dihukumnya pelaku pelanggaran HAM yang berat, tetapi juga tetap harus memperhatikan dampaknya terhadap kepentingan nasional suatu negara. Oleh karena itu, otoritas suatu negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan investigasi dapat melakukan penilaian apakah yurisdiksi universal akan memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap akses keadilan dan juga kepentingan negara. Penilaian tersebut dapat dilakukan terhadap misalnya dengan konsensus internasional terhadap seberapa berat suatu kejahatan, keinginan dari korban ataupun komunitas korban untuk mengakses keadilan, risiko bahaya apabila suatu kejahatan tidak dituntut di lokasi di mana pelaku berada, ketersediaan bukti-bukti, perlindungan terhadap saksi dan korban, serta dampak terhadap kedudukan dan juga reputasi negara yang melakukan penuntutan dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penuntutan [vide keterangan Ahli Devika Hovel dalam persidangan tanggal 8 Februari 2023]. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, yurisdiksi universal bukanlah sesuatu yang bersifat absolut, tetapi harus diseimbangkan dengan kewajiban internasional dan juga kepentingan-kepentingan lainnya dari suatu negara, sehingga suatu negara dapat menolak melaksanakan yurisdiksi universal apabila tidak dimungkinkan oleh dinamika politik, sosial dan ekonomi secara global atau kebutuhan dan kepentingan lainnya (rapidly changing situation). Di satu sisi, terlebih lagi apabila hal tersebut berpotensi mengganggu kepentingan nasional dari suatu negara, dan di sisi lain juga belum tentu dapat secara efektif memberikan rasa keadilan bagi para korban pelanggaran HAM yang berat.
[3.16.4] Bahwa berdasarkan uraian mengenai tantangan, potensi, dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan yurisdiksi universal oleh suatu negara, maka menurut Mahkamah, penerapan yurisdiksi universal bukanlah satu-satunya forum untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat lintas negara karena adanya potensi disalahartikan sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan negara yang malah akan menimbulkan permasalahan lain dalam hubungan diplomatik antar negara dan memengaruhi kredibilitas suatu negara dalam pergaulan internasional. Oleh karena itu, akan lebih baik apabila yurisdiksi universal diselenggarakan di tingkat kawasan/regional karena kedekatan dengan tempat terjadinya kejahatan serta ketersediaan barang bukti sehingga akan memudahkan untuk melakukan pengaturan-pengaturan antarpihak [vide keterangan Ahli Cheah W.L yang disampaikan dalam persidangan tanggal 8 Februari 2023]. Dalam kaitan ini, menarik forum penyelesaian pelanggaran HAM yang berat lintas negara pada tingkat regional akan lebih memberikan kepastian mengenai tanggung jawab negara yang timbul berdasarkan sebuah perjanjian internasional tanpa ada intervensi terhadap yurisdiksi suatu negara. Ketika negara-negara bersepakat untuk menundukkan diri dalam sebuah perjanjian, tidak ada lagi anggapan atau penilaian adanya perbedaan antara negara maju dan negara berkembang. Dengan kesepakatan demikian, setiap negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dan terikat pada pengaturan yang telah disepakati bersama. Dalam kaitan ini, pengaturan mengenai mekanisme pengadilan atau hukum acara sampai dengan model pemidanaan pelaku adalah merupakan kesepakatan dari masing-masing negara dalam suatu kawasan melalui sebuah perjanjian internasional.
Berdasarkan uraian di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan menghilangkan frasa “oleh warga negara Indonesia” dalam Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU 26/2000 agar UU 26/2000 dapat menerapkan prinsip yurisdiksi universal sehingga Pengadilan HAM Indonesia dapat mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh warga negara manapun adalah tidak beralasan menurut hukum.
[3.17] Menimbang bahwa berkenaan dengan adanya fakta yang terungkap dalam persidangan terkait asas universal dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), di mana para Pemohon mengaitkan antara asas universal dalam Pasal 6 KUHP (baru) 167 tersebut dengan inkonstitusionalitas norma frasa “oleh warga negara Indonesia” dalam Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU 26/2000, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan pendirian mengenai KUHP (baru) tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023, yang diikuti oleh putusan-putusan selanjutnya sebagai berikut:
[3.6.3] “…Oleh karena itu, apabila hal ini dikaitkan dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan, hal yang dialami oleh Pemohon, telah ternyata hak konstitusional Pemohon tersebut belum ada kaitannya dengan berlakunya norma undang-undang, in casu UU 1/2023. Dengan kata lain, pasal-pasal yang ada dalam UU 1/2023 yang diajukan pengujian oleh Pemohon terdapat dalam Undang-Undang yang belum berlaku dan dengan sendirinya belum mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 87 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU 12/2011) yang menyatakan, “Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan”. Berkaitan dengan itu, Pasal 624 UU 1/2023 menyatakan, “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”. Dengan demikian, Undang-Undang a quo belum berdampak terhadap adanya anggapan kerugian konstitusional, baik secara potensial, apalagi secara aktual kepada Pemohon.
[3.6.7] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Namun demikian, seandainyapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, dan Mahkamah dapat masuk untuk mempertimbangkan pokok permohonan, namun oleh karena ketentuan Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2), dan Pasal 509 huruf a dan huruf b UU 1/2023 merupakan ketentuan norma yang belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat, Mahkamah akan berpendirian bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan yang premature”.
Berdasarkan kutipan putusan a quo, ketentuan Pasal 6 KUHP (baru) yang dipersoalkan oleh para Pemohon dalam kaitan dengan inkonstitusionalitas norma frasa “oleh warga negara Indonesia” dalam Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU 26/2000 yang tidak menerapkan yurisdiksi universal, merupakan norma yang belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Seandainyapun KUHP telah berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat, quad non, menurut Mahkamah, pengaturan mengenai asas universal dalam KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 6 KUHP (baru) merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk melindungi kepentingan 168 hukum nasional dan/atau kepentingan hukum negara lain yang sebelumnya juga telah diatur dalam norma Pasal 4 ayat (2) KUHP yang masih berlaku (lama).
[3.17.1] Bahwa rumusan Pasal 6 KUHP (baru) menyatakan, “Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai Tindak Pidana dalam UndangUndang.” Pengaturan pasal a quo tidak dapat dilepaskan dari kerangka politik hukum penyusunan KUHP dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi yang dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 [vide Penjelasan Umum KUHP (baru) alinea ketiga]. Perumusan Pasal 6 KUHP (baru) merupakan upaya rekodifikasi atas berbagai ketentuan pidana dalam perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP berdasarkan konvensi internasional yang telah disahkan oleh Indonesia, seperti konvensi internasional mengenai uang palsu, konvensi internasional mengenai laut bebas dan hukum laut yang di dalamnya mengatur tindak pidana pembajakan laut, dan sebagainya [vide Penjelasan Pasal 6 KUHP (baru)]. Oleh karena itu, Pasal 6 KUHP (baru) a quo menjadi dasar keberlakuan (legalitas) suatu tindak pidana yang berasal atau berlandaskan pada konvensi internasional sepanjang tindak pidana tersebut telah ditetapkan atau diatur dalam KUHP. Namun demikian, keberlakuan Pasal 6 KUHP (baru) a quo tidak dapat serta merta dijadikan dasar perluasan kewenangan dilakukannya penuntutan pelanggaran HAM yang berat oleh Pengadilan HAM Indonesia. Dengan demikian, menjadi jelas adanya perbedaan konteks antara asas universal dalam Pasal 6 KUHP (baru) sebagai dasar keberlakuan hukum pidana umum dan penerapan yurisdiksi universal untuk memperluas ruang lingkup dan kewenangan pengadilan HAM di Indonesia.
[3.17.2] Bahwa terlebih lagi, keberlakuan asas universal dalam Pasal 6 KUHP (baru) juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 9 KUHP (baru) yang menyatakan, “Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut perjanjian internasional yang berlaku”. Berkenaan dengan apa yang dipersoalkan para Pemohon, telah pula dijelaskan dalam KUHP (baru) bahwa dimasukkannya esensi tindak pidana khusus dalam perumusan KUHP (baru) tidak menghilangkan sifat kekhususannya dengan pengaturan yang dinyatakan:
“Dengan sistem perumusan Tindak Pidana di atas, untuk Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, Tindak Pidana narkotika dikelompokkan dalam 1 (satu) bab tersendiri yang dinamai "Bab Tindak Pidana Khusus". Penempatan dalam bab tersendiri tersebut didasarkan pada karakteristik khusus, yaitu:
a. dampak viktimisasinya (Korbannya) besar;
b. sering bersifat transnasional terorganisasi (Transnational Organized Crime);
c. pengaturan acara pidananya bersifat khusus;
d. sering menyimpang dari asas umum hukum pidana materiel;
e. adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus (misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia);
f. didukung oleh berbagai konvensi internasional, baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi; dan
g. merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (super mala per se) dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat (strong people condemnation).
Dengan pengaturan "Bab Tindak Pidana Khusus" tersebut, kewenangan yang telah ada pada lembaga penegak hukum tidak berkurang dan tetap berwenang menangani Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, dan Tindak Pidana narkotika [vide Penjelasan Umum KUHP]”.
Dengan demikian, pelanggaran HAM yang berat merupakan tindak pidana khusus yang masih tetap tunduk pada UU 26/2000. Hal ini telah ditegaskan pula dalam Pasal 620 KUHP (baru) yang menyatakan, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Bab tentang Tindak Pidana Khusus dalam UndangUndang ini dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang masing-masing.” Dengan demikian, UU 26/2000 tetap merupakan UU yang mengatur tindak pidana khusus untuk Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia, sehingga pelaksanaan penegakan hukum atas pelaku pelanggaran HAM yang berat tetap didasarkan pada UU 26/2000. Terlebih lagi, pembentukan UU 26/2000 memang tidak didesain dengan dimaksudkan menganut prinsip yurisdiksi universal sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.15.2] di atas.
[3.18] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma frasa “oleh warga negara Indonesia” dalam Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU 26/2000 yang dikaitkan oleh para Pemohon dengan konflik yang terjadi di Myanmar yang menimbulkan pelanggaran HAM yang berat bagi etnis Rohingya, Mahkamah juga tidak dapat menutup mata terhadap permasalahan/konflik tersebut dan mengapresiasi kepedulian yang dilakukan para Pemohon dalam mendorong penegakan HAM atas pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Myanmar. Terhadap hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk turut serta secara aktif dalam menyelesaikan persoalan tersebut, baik dengan pola diplomasi Government to Government maupun dengan menyuarakan dalam forum yang lebih besar. Pemerintah Indonesia juga membangun kamp pengungsian dan memasok kebutuhan logistik serta obat-obatan bagi para pengungsi Rohingya yang singgah di wilayah NKRI serta secara nyata membangun Rumah Sakit Indonesia di Myaung Bwe. Upaya Indonesia tersebut, dilakukan dengan senantiasa mendorong keterlibatan negara-negara anggota ASEAN dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar serta mendorong partisipasi aktif negara-negara tetangga sebagai bentuk ikut serta menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana tujuan bernegara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma frasa “oleh warga negara Indonesia” dalam Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU 26/2000 telah ternyata tidak bertentangan dengan hak untuk hidup, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan kedudukan di hadapan hukum serta tidak menimbulkan diskriminasi hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430