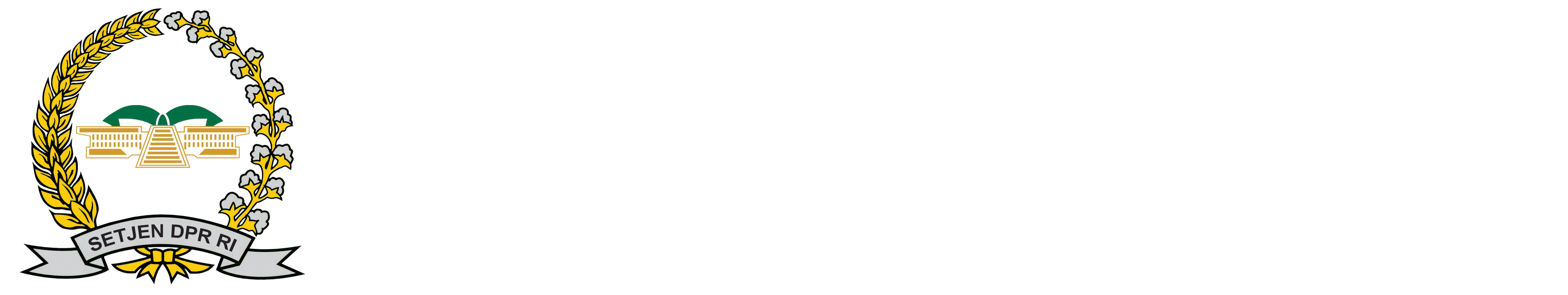
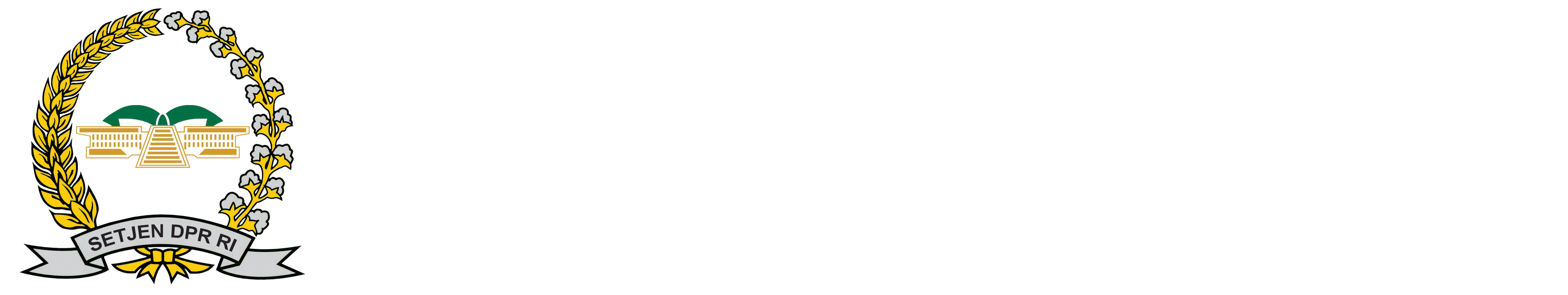

Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H. (Dosen pada Universitas Presiden), untuk selanjutnya disebut Pemohon.
Pasal Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1)
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.
Bahwa terhadap pengujian materiil UU Perlindungan Saksi dan Korban dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya, hal ini sebagaimana tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, antara lain, untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan tersebut haruslah dimaknai sebagai perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa kecuali, termasuk kepada para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
Bahwa salah satu pihak dalam proses peradilan pidana yang secara khusus perlu diberikan perlindungan adalah saksi dan korban sebagaimana termuat dalam UU 31/2014. Hal ini didasarkan pada mendesaknya kebutuhan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana. Kebutuhan ini dilandasi oleh kenyataan banyaknya kasus yang tidak dapat diungkap dan tidak selesai karena saksi dan korbannya tidak bersedia memberikan kesaksian kepada penegak hukum akibat ancaman dari pihak tertentu [vide Konsiderans Menimbang huruf a dan Penjelasan Umum UU 31/2014]. Oleh karenanya perlu ada pengaturan yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban yang pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi, korban, pelapor maupun saksi yang terlibat tindak pidana, dalam memberikan keterangan pada semua tahap proses peradilan pidana sehingga kebenaran material akan tercapai dan keadilan bagi masyarakat dapat terwujud. Terlebih lagi, perlindungan bagi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana belum diatur secara khusus. Sebab, Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dari kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan terhadap saksi dan korban diatur dalam undang-undang tersendiri [vide Penjelasan Umum UU 31/2014]. Perlindungan demikian, sejalan dengan esensi Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
Bahwa berdasarkan uraian di atas telah jelas UU 31/2014 merupakan ketentuan perundang-undangan yang bersifat lex specialis, hal ini tampak pada judul undang-undang itu sendiri yakni “Perlindungan Saksi dan Korban” yang artinya ketentuan perundang-undangan tersebut spesifik mengatur hal-hal yang terkait dengan syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan/atau korban yang sebelumnya terbagi-bagi dalam beberapa peraturan. Hal ini pun ditegaskan pula dalam Pasal 2 UU 31/2014 bahwa “Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahapan proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan”. Terkait dengan norma a quo, sama sekali tidak diubah meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 13/2006) diubah dengan UU 31/2014. Oleh karena itu, nomenklatur utama yang disebutkan dalam ketentuan umum UU a quo sesuai dengan judul UU adalah “saksi” dan “korban”. Saksi dimaksud adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri [vide Pasal 1 angka 1 UU 31/2014 juncto Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP]. Berkenaan dengan pengertian saksi ini, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Agustus 2011 Paragraf [3.13] menyatakan:
[3.13] Menimbang bahwa mengenai pengertian “saksi” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 26 dan angka 27 juncto Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, berdasarkan penafsiran menurut bahasa (gramatikal) dan memperhatikan kaitannya dengan pasal-pasal lain dalam KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Secara ringkas, Mahkamah menilai yang dimaksud saksi oleh KUHAP tersebut adalah hanya orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan atau didakwakan;
Menurut Mahkamah, pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP saja. Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan. Padahal, konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu; melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar terjadi. Dalam kontekspembuktian apakah suatu perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi; dan pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak meIihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa;
Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (a de charge) bagi tersangka atau terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya;
Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses;
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, Mahkamah telah menyatakan dalam amar Putusan a quo pemaknaan ”saksi” dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP yang pada pokoknya termasuk orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan pengertian korban dalam UU 31/2014 adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana [vide Pasal 1 angka 2 UU 31/2014]. Sistematika pengaturan pengertian/definisi dalam UU 31/2014 tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menentukan bahwa “ketentuan umum” berisi: a) batasan pengertian atau definisi; b) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab [vide angka 98 Lampiran II UU 12/2011]. Oleh karena fokus pengaturan UU 13/2006 adalah pada saksi dan korban sehingga dalam pengaturan UU a quo tidak terdapat pengaturan berkenaan dengan perlindungan terhadap “ahli”.
Adanya pengaturan mengenai “ahli” baru muncul dalam perubahan UU 13/2006 yaitu UU 31/2014. Dengan merujuk pada Penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU 31/2014, “Yang dimaksud dengan “ahli” adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan” [vide Penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU 31/2014]. Bahwa selanjutnya keterangan ahli merupakan salah satu di antara alat bukti yang memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli adalah salah satu alat bukti yang sah. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keterangan Ahli adalah “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ahli adalah orang yang memiliki “keahlian khusus” tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP di atas, apabila dicermati, KUHAP tidak mengatur secara khusus mengenai apa syarat didengarkannya sebagai keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. Adapun yang dijelaskan dalam KUHAP adalah orang yang memiliki “keahlian khusus” tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan. Keahlian khusus tersebut dalam hal ini dapat ditafsirkan berkaitan dengan kemampuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan terhadap suatu objek tertentu yang diketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya dalam rangka membantu proses peradilan pidana.
[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil pokok Pemohon yang menyatakan Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan dalil yang pada pokoknya Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 merupakan norma yang tidak pasti, tidak adil, dan diskriminatif. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
[3.11.1] Bahwa norma Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon menyatakan, “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik” adalah norma yang mengatur mengenai perlindungan bagi saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor untuk tidak dituntut secara hukum (pidana maupun perdata) sepanjang informasi/kesaksian tersebut diberikan dengan iktikad baik yakni dengan tidak memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat. Hal demikian menjadi penting diberikan berkenaan dengan peran dan posisi mereka dalam proses peradilan pidana, yakni berkontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu.
Saksi misalnya, memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi yang hanya akan fair jika saksi tidak dalam kondisi ketakutan atas keberlanjutan hidupnya, sehingga kewajiban tersebut harus diimbangi pula dengan kewajiban dari sistem peradilan pidana untuk menyediakan lingkungan yang kondusif bagi saksi untuk dapat memberikan keterangannya secara bebas dan tanpa intimidasi. Adapun terkait dengan korban, kesuksesan dalam pengungkapan dan penuntutan kejahatan seperti kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence), dan perdagangan orang ditentukan oleh korban yang akan memberikan keterangan di pengadilan yang tidak jarang akan dihadapkan dengan pelaku sehingga memerlukan prosedur khusus yang memberikan perlindungan bagi korban dalam kerangka asas peradilan yang terbuka. Begitu pula dengan saksi pelaku, yang merupakan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang mau bekerjasama dengan penegak hukum dan memiliki iktikad baik untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama, tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti bersalah, tetapi keterangannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan, sehingga diperlukan suatu jaminan perlindungan agar mereka dapat memberikan keterangan secara lengkap dan jelas [vide Pasal 10 ayat (2) UU 31/2014]. Bahkan, terhadap saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan berupa pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya; pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya [vide Pasal 10A UU 31/2014]. Terlebih lagi, saksi yang menjadi pelaku tindak pidana dapat mengundurkan diri atau menolak untuk menjadi saksi dalam perkara yang sama di persidangan [vide Pasal 168 huruf c KUHAP]. Perlakuan demikian apabila dikaitkan dengan hukum acara pidana menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat serta negara, karena pada dasarnya dalam hukum pidana, individu dan/atau masyarakat berhadapan langsung dengan negara. Hubungan ini menempatkan individu dan/atau masyarakat dalam hal ini baik saksi, korban, maupun saksi pelaku pada posisi yang lebih lemah. Artinya, di satu sisi, saksi yang tidak memberikan keterangan yang sebenarnya akan diancam dengan sumpah palsu, namun di sisi lain saksi yang memberikan keterangan yang sebenarnya berpotensi terancam keselamatan jiwanya oleh pelaku tindak pidana atau pihak lain. Oleh karenanya, UU 31/2014 memberikan perhatian lebih berupa perlindungan yang diperlukan agar proses peradilan pidana dapat berjalan tanpa ada hambatan.
Sekalipun UU 31/2014 menitikberatkan pengaturannya pada saksi dan korban, namun juga sebagai bagian dari upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, UU a quo juga perlu memberikan perlindungan kepada pelapor, sehingga terhadap pelapor pun tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya dengan iktikad baik. Pengaturan mengenai pemberian perlindungan hukum ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana, sehingga perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu [vide Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Umum UU 13/2006]. Berkenaan dengan pengaturan mengenai perlindungan bagi pelapor ini mendapatkan penegasan dalam perubahan UU 13/2006 dengan memberikan batasan pengertian atau definisi pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi [vide Pasal 1 angka 4 UU 31/2014]. Oleh karena itu, pengertian pelapor pada hakikatnya tidak berbeda dengan pemaknaan saksi.
[3.11.2] Bahwa kedudukan korban tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap proses peradilan pidana. Berbeda dengan KUHAP, UU 31/2014 mengatur perlindungan terhadap saksi dan/atau korban, baik itu terhadap korban yang juga menjadi saksi, korban yang tidak menjadi saksi dan juga anggota keluarganya. Adapun terkait saksi pelaku dan pelapor, meskipun tidak juga diatur secara eksplisit dalam KUHAP namun dalam praktiknya, istilah tersebut telah muncul dan dikenal dalam praktik Hukum Acara Pidana. Sehingga secara umum, baik koban, saksi pelaku, dan/atau pelapor dapat berkedudukan juga sebagai saksi.
Bahwa berkaitan dengan eksistensi saksi, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Sub-Paragraf [3.16.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 November 2022 menyatakan:
[3.16.2] … Terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri [vide Pasal 1 angka 26 KUHAP]. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu [vide Pasal 1 angka 27 KUHAP]. Oleh karena itu, apabila dicermati secara saksama dari terminologi pengertian tentang saksi dan keterangan saksi tersebut dapat dimaknai saksi adalah subjek hukum atau pihak yang keberadaannya diperlukan untuk memberi keterangan atas adanya suatu tindak pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi yang bersangkutan. Dengan demikian, pemberian keterangan seseorang sebagai saksi dalam semua tingkatan pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan peradilan) sesungguhnya secara limitatif dalam perspektif memberi kejelasan atas adanya tindak pidana yang disaksikan oleh saksi yang bersangkutan.
Lebih lanjut, berkaitan dengan saksi, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 8 Agustus 2011, telah memberikan pemaknaan saksi yang lebih luas dalam perspektif saksi yang meringankan tersangka atau terdakwa (saksi a de charge) dan saksi yang memberatkan tersangka atau terdakwa (saksi a charge), Mahkamah berpendirian pada pokoknya, saksi tidak hanya yang mendengar, melihat dan merasakan sendiri atas adanya peristiwa pidana, akan tetapi menjadi kewajiban penyidik sejak tingkat pemeriksaan penyidikan untuk mengakomodir saksi-saksi yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa sepanjang dapat membantu meringankan kesalahan tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, sejak di tingkat penyidikan saksi yang meringankan tersangka atau terdakwa meskipun tidak mendengar, melihat dan merasakan sendiri atas peristiwa pidana yang bersangkutan, namun apabila sepanjang yang didengar, dilihat dan dirasakan dapat memberikan keuntungan bagi tersangka atau terdakwa, maka keterangannya dapat dikategorikan sebagai keterangan saksi..”.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, keberadaan saksi dalam kaitan memberikan keterangan adalah dalam rangka memberikan kejelasan atas adanya tindak pidana yang diketahui oleh saksi yang bersangkutan (berdasarkan fakta). Sehingga dalam hal ini, saksi wajib untuk memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Dengan kata lain, keterangan saksi harus dilandasi pada semangat untuk mengungkap kebenaran materiil dalam setiap proses peradilan pidana sehingga dalam proses pemeriksaan dapat diungkap perbuatan nyata yang dilakukan terdakwa dan derajat kesalahan terdakwa.
Seorang saksi dapat dijatuhi hukuman apabila saksi tersebut terbukti menolak menjadi seorang saksi suatu perkara yang melibatkan dirinya dan/atau memberikan keterangan palsu atau menambah unsur-unsur kebohongan di dalam kesaksiannya di persidangan [vide Pasal 224 ayat (1) dan Pasal 242 butir 1 dan butir 2 KUHP]. Dalam posisi tersebut, perlindungan kepada saksi pada semua tahap proses peradilan sangatlah diperlukan, baik terkait fisik, psikis, maupun perlindungan dari adanya tuntutan hukum sehingga saksi dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang diketahuinya dengan rasa aman tanpa adanya tekanan dari pihak manapun [vide Pasal 4 UU 31/2014].
[3.11.3] Bahwa berbeda dengan saksi, definisi ahli sendiri tidak dijelaskan secara khusus dalam KUHAP, begitu pula dalam UU 31/2014. Namun demikian, Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan, “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ahli ialah seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Oleh karena itu, seseorang dapat dikatakan sebagai ahli setidak-tidaknya harus memenuhi berbagai kriteria. Namun berdasarkan pengertian ahli sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, tidak mengatur secara khusus mengenai apa syarat didengarkannya sebagai keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. Adapun yang dijelaskan dalam KUHAP adalah selama ia memiliki “keahlian khusus” tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan. Keahlian khusus tersebut dalam hal ini dapat ditafsirkan berkaitan dengan kemampuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan terhadap suatu objek tertentu yang diketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya dalam rangka membantu proses peradilan pidana. Dengan demikian, tidak terdapat kriteria yang jelas mengenai siapa yang dapat disebut sebagai ahli. KUHAP hanya menyatakan terdapat keahlian khusus yang berarti terkait dengan kemampuan akan pengetahuan yang secara spesifik dimiliki karena pendidikan atau pengalaman kerjanya. Karena ahli pada dasarnya dibutuhkan dalam setiap proses persidangan tidak terkecuali perkara pidana untuk membuat terang suatu peristiwa hukum tertentu. Untuk itu, ahli setidak-tidaknya harus memiliki kriteria atau validitas antara lain: (1) berpendidikan dan memiliki pengalaman yang spesifik dengan bidang yang telah digeluti; (2) terdapat bukti formal mengenai keahlian yang dimiliki; (3) terdapat rekam jejak yang baik terkait dengan integritasnya dalam menyampaikan keahliannya. Hal demikian menjadi penting agar keterangan yang disampaikan ahli berasal dari ahli yang berkompeten, objektif, dan tidak memihak (independen) serta memiliki integritas yang tinggi sehingga keterangan yang disampaikan tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh pihak yang memintanya sebagai ahli ataupun dipengaruhi oleh pihak lainnya dan dapat dipertanggungjawabkan selain kepada bangsa dan negara, juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pertimbangan itulah, ahli diberikan kebebasan untuk berpendapat sesuai dengan keahliannya namun tidak dalam konteks menyampaikan fakta, sehingga keterangan ahli tidak ada relevansinya dengan keterdesakan atau perasaan terancam seperti halnya yang dirasakan atau dialami oleh saksi, korban, atau pelapor.
Bahwa sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan ahli memiliki nilai pembuktian yang bebas atau tidak mengikat hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinan hakim. Dalam hal ini, keterangan ahli berfungsi menjadi alat bantu yang positif dan konstruktif bagi hakim untuk menemukan kebenaran dan hakim bebas memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan keterangan ahli tersebut. Sehingga apabila hakim merasa keterangan ahli bertentangan dengan keyakinannya maka ia dapat tidak mempertimbangkan keterangan ahli tersebut.
[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, setelah Mahkamah mencermati petitum Pemohon berkenaan dengan perlindungan saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor yang diatur dalam norma Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 di mana Pemohon memohon kepada Mahkamah agar dimasukkan pula perlindungan ahli, dengan cara menyisipkan perlindungan untuk ahli agar ahli tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas keterangan yang diberikan dengan iktikad baik ke dalam Pasal a quo. Terhadap petitum tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama esensi Pasal 10 ayat (1) UU 13/2006 yang diubah dengan UU 31/2014 justru materi muatannya adalah dalam rangka menegaskan perlindungan saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor agar tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik, sebagaimana maksud dibentuknya UU 31/2014. Penegasan dimaksud dimaktubkan dalam Pasal 10 ayat (2) UU 31/2014 yang menyatakan “Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Oleh karena itu, apabila norma Pasal 10 UU a quo diubah dengan menyisipkan kata “ahli” sebagaimana petitum Pemohon maka hal tersebut justru akan merusak sistematika dan substansi pokok dalam norma Pasal a quo yang berkaitan dengan pasal-pasal lainnya dalam UU 31/2014.
Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sesungguhnya telah diakomodasi dalam perubahan UU 13/2006 sejalan dengan maksud Konsiderans Menimbang huruf b UU 31/2014 yang menyatakan “untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli”, di mana maksud tersebut kemudian dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU 31/2014 yang menyatakan:
“Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang- Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat.
Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (justice collaborator), Pelapor (whistle-blower), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan. Tindak pidana tertentu tersebut di atas yakni tindak pidana pelanggaraan hak asasi.
Artinya, esensi pokok UU 31/2014 sekalipun telah diubah adalah tetap pada keberadaan perlindungan saksi dan korban yang merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Adanya pengaturan penambahan unsur di luar saksi dan korban, yaitu dengan memasukkan ahli pada pokoknya hanya dikaitkan dengan upaya pengungkapan tindak pidana yang bersifat khusus, yakni tindak pidana transnasional yang terorganisir. Oleh karena itu, dalam perubahan UU 13/2006 terdapat perluasan subyek yang dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), namun perluasan tersebut hanya terkait dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengungkapan tindak pidana transnasional yang terorganisir, termasuk pihak dimaksud adalah ahli berdasarkan Keputusan LPSK. Hal ini sejalan dengan maksud pengaturan dalam Pasal 5 ayat (3) UU 31/2014 yang menyatakan.
“Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.
Tindak pidana dalam kasus tertentu dimaksud dijelaskan antara lain, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya [vide Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU 31/2014]. Dengan demikian, telah terang bahwa pengaturan dalam Pasal 10 UU 31/2014 merupakan pengaturan yang bersifat umum untuk memberikan perlindungan kepada saksi, korban, saksi pelaku dan/atau korban dalam tindak pidana apapun, sedangkan perlunya diberikan perlindungan terhadap ahli oleh LPSK berdasarkan Keputusan LPSK hanya untuk tindak pidana tertentu dalam rangka memberikan perlindungan kepada ahli untuk dapat bebas berpendapat sesuai dengan keahlian dan keyakinan yang dimilikinya terhadap suatu perkara sehingga membuat suatu perkara pidana tertentu menjadi terang dan jelas.
Dengan demikian, tidak terdapat persoalan ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan Pemohon karena beranggapan tidak adanya perlindungan terhadap dirinya tatkala menjadi ahli. Pada prinsipnya sebagai negara hukum, prinsip due process of law sebagai perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. Konstitusi telah menegaskan bahwa siapapun warga negara Indonesia dilindungi dari rasa aman dan diberikan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [vide Pasal 28G ayat (2) UUD 1945]. Dalam kaitan ini, tugas negara memberikan perlindungan terhadap semua pihak yang terkait dalam proses peradilan pidana, termasuk ahli, namun dengan syarat, tata cara, dan pengaturan yang berbeda.
[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 telah ternyata tidak menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi yuridisnya, dalil Pemohon mengenai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 juga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya.
Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430