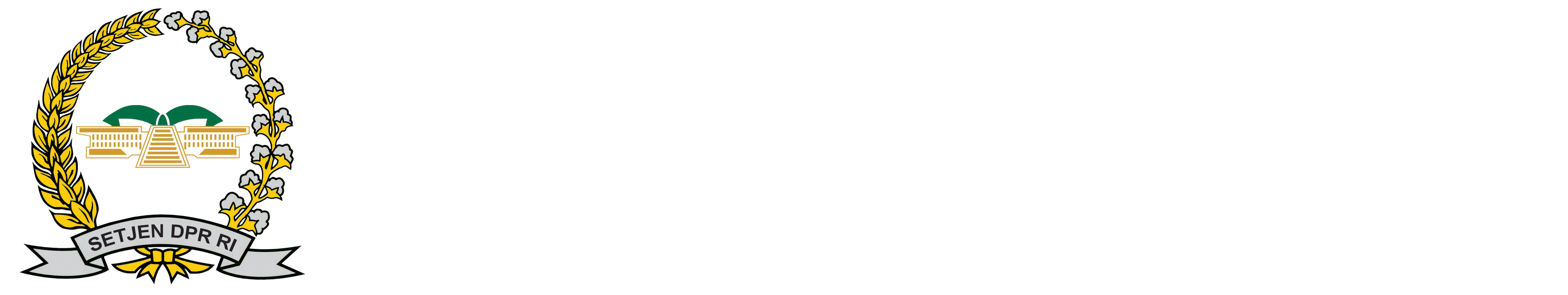
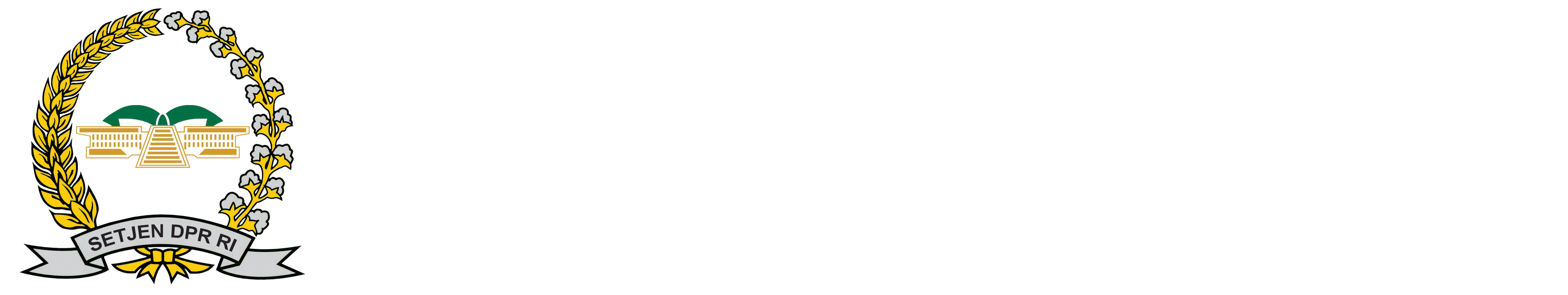

Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H. untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.
Pasal 14 ayat (1) huruf i dan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995
Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 41/PUU-XIX/2021, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.
Bahwa terhadap pengujian UU 12/1995 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
[3.13] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan a quo dapat diajukan kembali maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dan Penjelasannya bersifat multitafsir dan menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap narapidana sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Terhadap konstitusionalitas norma Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 pada Sub-paragraf [3.8.5] dan Sub-paragraf [3.8.7], sebagai berikut:
[3.8.5] Bahwa apabila dibaca dan ditelaah ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995, hak-hak narapidana sebagaimana termaktub di dalam huruf a sampai dengan huruf m termasuk hak atas remisi adalah hak hukum (legal rights) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat- syarat tertentu. Dengan demikian, berarti, hak-hak tersebut, termasuk remisi, bukanlah hak yang tergolong ke dalam kategori hak asasi manusia (human rights) dan juga bukan tergolong hak konstitusional (constitutional rights). Apabila dikaitkan dengan pembatasan, jangankan terhadap hak hukum (legal rights), bahkan hak yang tergolong hak asasi (human rights) pun dapat dilakukan pembatasan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan diatur dengan undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, dikaitkan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa norma a quo diskriminatif, Mahkamah telah berulang kali mengemukakan bahwa suatu norma dikatakan mengandung materi muatan yang bersifat diskriminatif apabila norma undang-undang tersebut memuat rumusan yang membedakan perlakuan antara seseorang atau sekelompok orang dengan seseorang atau sekelompok orang lainnya semata-mata didasarkan atas perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya [vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia]. Hal demikian sama sekali tidak terkandung dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995.
[3.8.7] Bahwa rumusan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995, secara khusus Pasal 14 ayat (1) huruf i, telah sangat jelas sebab isinya hanya memuat rincian tentang hak-hak narapidana sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain atau diberi pemaknaan berbeda selain apa yang tersurat dalam rumusan norma a quo, lebih-lebih untuk ditafsirkan atau didalilkan diskriminatif. Secara teknik perundang-undangan, Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 telah memenuhi asas kejelasan rumusan maupun asas kejelasan tujuan. Dikatakan demikian, sebab, norma a quo secara jelas memerinci hak-hak apa saja yang dapat diberikan kepada narapidana sesuai dengan filosofi pemasyarakatan yang dianut oleh undang-undang a quo.
Pendapat Mahkamah mengenai konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XV/2017 pada Sub-paragraf [3.12.1], sebagai berikut:
Lebih lanjut, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 pada sub-paragraf [3.8.5] di atas, telah pula ditegaskan bahwa remisi adalah hak hukum (legal rights) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Artinya, remisi bukanlah hak yang tergolong ke dalam kategori hak asasi manusia (human rights) dan juga bukan tergolong hak konstitusional (constitutional rights) sehingga dapat dilakukan pembatasan terhadapnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian jelas bahwa pembatasan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat dan memperoleh remisi untuk narapidana tidaklah melanggar hak narapidana. Namun dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa penilaian atas syarat-syarat untuk memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat untuk narapidana dimulai sejak narapidana yang bersangkutan memperoleh status sebagai narapidana dan menjalani masa pidana.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 tidak bersifat diskriminatif karena hanya memuat rincian tentang hak-hak narapidana, termasuk hak untuk mendapatkan remisi (huruf i), tanpa disertai kondisi atau persyaratan terpenuhinya hak tersebut. Pengaturan mengenai hak narapidana merupakan bentuk kehadiran negara dalam upaya untuk melindungi warga negaranya sekalipun berstatus sebagai narapidana. Artinya, negara bersikap pro-aktif untuk memberikan kebebasan dan keistimewaan tertentu yang ditetapkan dan ditegakkan oleh seperangkat aturan hukum. Kebebasan atau keistimewaan demikian tidak bersifat mendasar (asasi) dan berada di luar dari hak warga negara yang telah ditentukan dalam konstitusi. Oleh karenanya, pengaturan mengenai subjek, objek, persyaratan hingga perubahan dan pencabutan terhadapnya ditentukan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Dalam konteks demikian, pemberian hak hukum (legal rights) kepada sebagian kelompok masyarakat, secara logis dapat dinilai diskriminatif dari kacamata orang lain yang tidak memperoleh hak tersebut, sedangkan bagi si penerima (subjek) hak, penilaian mengenai timbulnya diskriminasi adalah ketika terdapat materi norma yang menentukan kondisi dan persyaratan tertentu atau dalam implementasi norma tersebut yaitu terkait dengan pemenuhan hak yang telah diberikan. Oleh karena Pemohon dalam hal ini merupakan subjek hak, in casu hak remisi, maka rumusan norma yang isinya hanya memuat rincian tentang hak-hak narapidana (termasuk Pemohon) menurut Mahkamah tidak mungkin ditafsirkan lain selain apa yang tersurat dalam rumusan norma a quo. Dengan demikian, Mahkamah kembali menegaskan bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 tidak bersifat multitafsir dan diskriminatif sehingga dalil Pemohon yang menyatakan norma a quo bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum;
[3.14] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 bersifat multitafsir dan menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap narapidana sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 hanya memuat tafsir resmi atas norma yang diatur dalam batang tubuh dan tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Penjelasan a quo lebih menegaskan bahwa (hak) remisi dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, karena pada saat UU 12/1995 ditetapkan, telah berlaku terlebih dahulu setidaknya 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang lebih teknis mengatur mengenai remisi di Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955 tentang Ampunan Istimewa dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh Dan Donor Darah. Oleh karena itu, uraian lebih lanjut mengenai pemberian hak remisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 adalah merujuk pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih teknis mengatur mengenai remisi yang juga masih berlaku setelah diundangkannya UU 12/1995. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 adalah tidak beralasan menurut hukum;
[3.15] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan bahwa akibat dari berlakunya Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 yang bersifat multitafsir telah membuka ruang adanya campur tangan pihak lain dalam penentuan pemberian (hak) remisi bagi narapidana yang lebih ketat dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah, permasalahan demikian bukanlah dikarenakan inkonstitusionalnya norma dalam UU 12/1995 yang dimohonkan pengujian, melainkan merupakan persoalan implementasi norma yang dialami oleh Pemohon, yaitu terkait dengan mekanisme pemberian remisi sebagaimana diatur dalam UU 12/1995 yang dikaitkan dengan salah satu peraturan pemerintah yang mensyaratkan bahwa setiap narapidana tindak pidana korupsi harus mendapatkan predikat sebagai justice collaborator untuk mendapatkan hak remisi. Terhadap hal demikian, Mahkamah perlu mengutip pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 pada Sub-paragraf [3.8.6], sebagai berikut:
[3.8.6] Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang a quo, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Kemudian PP a quo direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Secara substansial berkenaan dengan remisi Pemerintah menunjukkan kecenderungan untuk memperketat syarat pemberian remisi terhadap tindak pidana atau kejahatan khusus, termasuk korupsi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, remisi adalah hak hukum (legal rights) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995, Pemerintah berwenang untuk mengatur syarat pemberian remisi tersebut.
Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana telah dikutip di atas, telah jelas bahwa Pemerintah diberikan wewenang secara delegasi oleh Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995 untuk mengatur lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Pertanyaan kemudian adalah, apa saja pedoman atau batasan bagi Pemerintah dalam menyusun substansi norma peraturan pelaksana tersebut. Karena setelah Mahkamah mencermati beberapa permohonan yang pernah diajukan ke Mahkamah terkait dengan pengujian konstitusionalitas norma yang berkenaan dengan hak-hak narapidana, khususnya dalam hal ini adalah hak remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi, selalu mempermasalahkan adanya perlakuan diskriminasi dan melanggar hak-hak narapidana dalam pelaksanaan pemberian remisi yang diatur dalam peraturan pelaksananya dan bukan pada undang-undang induknya. Oleh karena itu, Mahkamah sebagai pelindung hak konstitusional warga negara sekaligus pengawal demokrasi juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat hak dan kewajiban dalam hukum publik yang demokratis sehingga meskipun permasalahan yang dialami dan didalilkan oleh Pemohon merupakan implementasi norma yang bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, Mahkamah memandang perlu menyampaikan pertimbangan sebagai berikut:
[3.15.1] Bahwa bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, telah berkembang pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar memenjarakan pelaku tindak pidana agar pelakunya jera, akan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Perkembangan pemidanaan ini sejalan dengan model hukum yang dikenal dengan model restorative justice (model hukum yang memperbaiki). Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga merupakan subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Namun yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai [vide Penjelasan Umum UU 12/1995]. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan harus dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak warga binaan serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, tidak sekedar mendasarkan pada konsep penjeraan dan pembalasan;
[3.15.2] Bahwa berdasarkan filosofi pemasyarakatan dan arah perkembangannya tersebut di atas, maka substansi rumusan norma yang terdapat pada peraturan pelaksana dari UU 12/1995 sebagai aturan teknis pelaksana harus mempunyai semangat yang sebangun dengan filosofi pemasyarakatan yang mengakomodir dan memperkuat pelaksanaan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta konsep restorative justice. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sejatinya hak untuk mendapatkan remisi harus diberikan tanpa terkecuali. Artinya, berlaku sama bagi semua warga binaan untuk mendapatkan haknya secara sama, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Penegasan mengenai hak warga binaan dalam sistem pemasyarakatan ini sangat penting, karena menurut Mahkamah, penahanan atas diri pelaku tindak pidana, termasuk dalam hal ini menempatkan warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan sekalipun, pada dasarnya merupakan perampasan hak untuk hidup secara bebas yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karenanya, selama menjalani penahanan seseorang tersebut harus tetap diberikan hak-hak yang bersifat mendasar dengan prinsip satu-satunya hak yang hilang adalah hak untuk hidup bebas sebagaimana halnya orang lain yang tidak sedang menjalani pidana. Meskipun demikian, pemberian hak tersebut tidak lantas menghapuskan kewenangan negara untuk menentukan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh warga binaan karena hak tersebut merupakan hak hukum (legal rights) sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.13] di atas. Namun, persyaratan yang ditentukan tidak boleh bersifat membeda-bedakan dan justru dapat menggeser konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang ditetapkan, selain juga harus mempertimbangkan dampak overcrowded di Lapas yang juga menjadi permasalahan utama dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, adanya syarat-syarat tambahan di luar syarat pokok untuk dapat diberikan remisi kepada narapidana, seharusnya lebih tepat dikonstruksikan sebagai bentuk penghargaan (reward) berupa pemberian hak remisi (tambahan) di luar hak hukum yang telah diberikan berdasarkan UU 12/1995. Sebab, pada dasarnya segala fakta dan peristiwa hukum yang terjadi berkaitan dengan suatu tindak pidana yang disangkakan maupun didakwakan kepada seseorang harus diperiksa di persidangan untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. Termasuk misalnya terdakwa yang dinilai tidak mau mengakui perbuatannya maupun tidak secara jujur mengakui keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana yang dimaksud, tentu akan menjadi salah satu hal yang memberatkan hukuman pidana. Oleh karenanya, sampai pada titik tersebut segala kewenangan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan persidangan pengadilan telah berakhir, dan selanjutnya menjadi ruang lingkup sistem pemasyarakatan, sehingga hal-hal tersebut kehilangan relevansinya apabila dikaitkan dengan syarat pemberian remisi bagi narapidana. Terlebih, kewenangan untuk memberikan remisi adalah menjadi otoritas penuh lembaga pemasyarakatan yang dalam tugas pembinaan terhadap warga binaannya tidak bisa diintervensi oleh lembaga lain, apalagi bentuk campur tangan yang justru akan bertolak-belakang dengan semangat pembinaan warga binaan. Artinya, lembaga pemasyarakatan di dalam memberikan penilaian bagi setiap narapidana untuk dapat diberikan hak remisi harus dimulai sejak yang bersangkutan menyandang status warga binaan, dan bukan masih dikaitkan dengan hal-hal lain sebelumnya. Sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, apapun jenis tindak pidana yang dilakukan seorang terdakwa maupun hal-hal yang meliputi dengan perbuatan yang dilakukan, seharusnya sudah selesai ketika secara komprehensif telah dipertimbangkan secara hukum dalam putusan pengadilan yang berakhir pada jenis dan masa pidana yang dijatuhkan (strafmaat) oleh hakim. Selanjutnya, bagi seorang terdakwa yang telah menerima jenis dan masa pidana tersebut yang berakibat putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap maka bagi terpidana yang menjalani pidana sebagai warga binaan akan memasuki babak kehidupan baru untuk menjalani pidana dalam rangka proses untuk dikembalikan di tengah masyarakat dengan hak-haknya yang harus dipenuhi tanpa ada pengecualian, sepanjang syarat-syarat pokok sebagaimana ditentukan dalam UU 12/1995 terpenuhi. Dalam konteks penjelasan suatu norma, penjelasan sebuah undang-undang juga tidak boleh menambahkan norma baru, apalagi menambah persyaratan yang tidak sejalan dengan norma pokok yang terdapat dalam undang-undang yang bersangkutan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-III/2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 serta angka 176 dan angka 177 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan];
[3.15.3] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995, Mahkamah tetap pada pendiriannya sebagaimana putusan-putusan sebelumnya. Namun, berkaitan dengan penegasan Mahkamah pada pertimbangan hukum sebelumnya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi di dalam melindungi hak konstitusional dan demokrasi warga negara, meskipun segala hal yang berkaitan dengan pertimbangan hukum di atas merupakan ranah implementasi norma yang bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;
[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai penghormatan atas hak asasi manusia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dan Penjelasannya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430