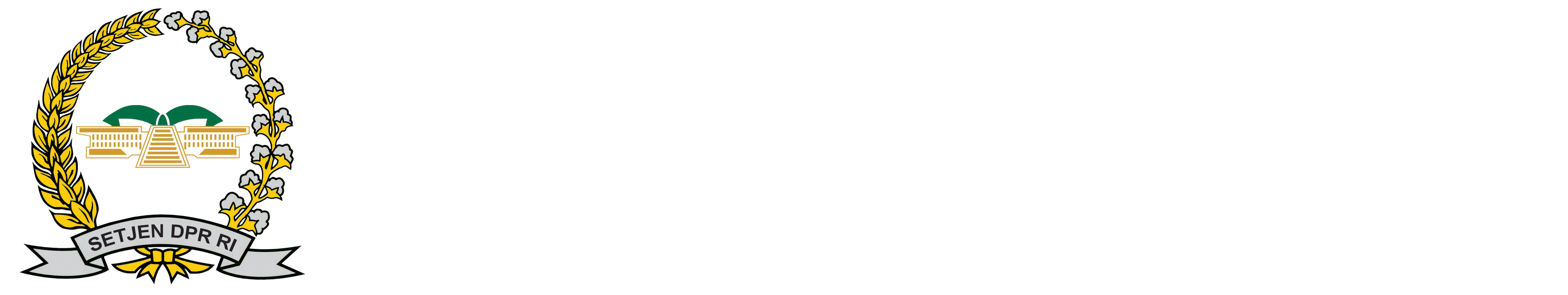
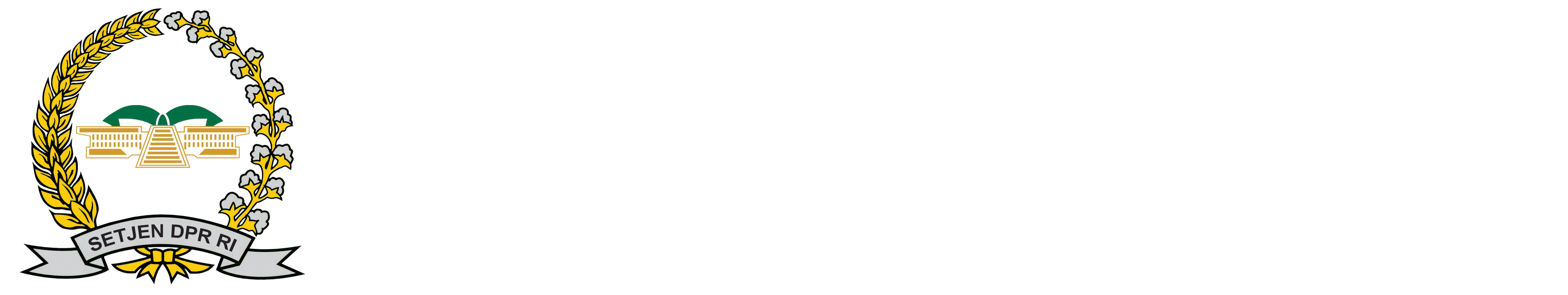

Krisman Dedi Awi Janul Fonataba, S. Sos., dan Darius Nawipa dalam hal ini diwakili oleh Habel Rumbiak, S. H., SpN., dan Ivan Robert Kairupan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kamasan, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.
Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU 21/2001
Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.
Bahwa terhadap pengujian UU 21/2001 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
[3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, bukti surat/tulisan dan keterangan para ahli yang diajukan Pemohon, dan kesimpulan Pemohon; keterangan DPR; keterangan Presiden; keterangan para ahli yang dihadirkan Mahkamah, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yang berkenaan dengan frasa “partai politik” pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU 21/2001, sebagai berikut:
[3.13.1] Bahwa otonomi khusus Provinsi Papua (termasuk Provinsi Papua Barat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang) diberikan berdasarkan UU 21/2001. Pemberian status otonomi khusus bagi Papua merupakan pelaksanaan amanat dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, yang menyatakan mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Irian Jaya melalui penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang [vide Bab IV huruf G angka 2]. Selain itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, antara lain menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan otonomi khusus melalui penetapan suatu undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Irian Jaya dengan memerhatikan aspirasi masyarakat selambat-lambatnya 1 Mei 2010. Di samping kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat di atas, otonomi khusus Provinsi Papua termasuk Provinsi Papua Barat yang diberikan berdasarkan UU 21/2001 juga merupakan amanat pelaksanaan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Dengan demikian pemberian otonomi khusus bagi Papua merupakan bagian dari pengakuan negara terhadap bentuk kekhususan suatu daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU 21/2001 antara lain sebagai berikut:
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besamya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan…
[3.13.2] Bahwa suatu daerah ditetapkan sebagai daerah khusus jika kekhususan daerah tersebut terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak dapat disamakan dengan daerah lainnya. Dengan kata lain, terdapat latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata sehingga diperlukan kekhususan dari daerah yang bersangkutan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam penentuan jenis dan ruang lingkup kekhususan yang didasarkan pada latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata yang mengharuskan diberikan kekhususan kepada suatu daerah adalah bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan nyata diberikannya kekhususan bagi daerah yang bersangkutan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VII/2010 bertanggal 2 Maret 2011]. Dalam konteks Papua yakni antara lain dengan mengingat bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia [vide Konsiderans “Menimbang” huruf h UU 21/2001].
[3.13.3] Bahwa berdasarkan latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata Papua maka pembentuk Undang-Undang melalui UU 21/2001 memberikan kekhususan kepada Papua seperti dalam bidang pemerintahan dan politik yang mencakup antara lain:
1. Adanya Majelis Rakyat Papua (MRP), yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan umat beragama [Pasal 5 ayat (2) UU 21/2001];
2. Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) merupakan nomenklatur yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, yaitu DPRD provinsi. Demikian pula terdapat perbedaan perekrutan anggota DPRP, yakni sebagian anggotanya diangkat, sedangkan sebagian lainnya dipilih melalui pemilihan umum [Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001];
3. Adanya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) di samping Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ini;
4. Perbedaan nomenklatur, yakni adanya distrik yang pada dasarnya adalah kecamatan di provinsi lain [Pasal 3 ayat (2) UU 21/2001];
5. Calon gubernur dan calon wakil gubernur harus orang asli Papua [Pasal 12 huruf a UU 21/2001].
Dengan demikian berdasarkan kekhususan tersebut tidak terdapat materi muatan yang mengatur mengenai pembentukan partai politik lokal di Papua sebagaimana di Provinsi Aceh sebagai salah satu kekhususan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU 11/2006);
[3.13.4] Bahwa jika Pasal 28 UU 21/2001 dibaca secara keseluruhan, sebenarnya kekhususan mengenai partai politik di Papua berkenaan dengan rekrutmen yang memrioritaskan orang asli Papua [vide Pasal 28 ayat (3) UU 21/2001] dan wajib meminta pertimbangan kepada Majelis Rakyat Papua [vide Pasal 28 ayat (4) UU 21/2001]. Berbeda dengan Aceh, meskipun diberi kekhususan pembentukan partai politik lokal, akan tetapi dalam hal mekanisme seleksi dan rekrutmen partai politik dilakukan secara mandiri oleh partai politik. Jadi, meskipun kedua daerah tersebut diberikan kekhususan namun jenis dan ruang lingkup kekhususan tidak harus selalu sama. Perbedaan tersebut didasarkan pada latar belakang dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah yang diberi status otonomi khusus oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian Pasal a quo tidak dapat dikatakan bersifat diskriminatif karena memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda.
Selain itu, dengan kekhususan dalam hal rekrutmen politik oleh partai politik nasional yang memrioritaskan masyarakat asli Papua dan mewajibkan meminta pertimbangan kepada Majelis Rakyat Papua sesuai dengan semangat otonomi khusus Papua yang menekankan peran penting bagi orang-orang asli Papua dan menempatkan orang asli Papua sebagai subjek utama, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UU 21/2001. Lagi pula, melalui partai politik nasional keterlibatan orang asli Papua di tingkat politik nasional lebih terjamin karena kaderisasi tidak terbatas di tingkat lokal dan karir politik memungkinkan sampai di tingkat nasional, sehingga aspirasi atau kepentingan terkait dengan Papua lebih mudah tersalurkan. Dengan demikian meskipun tidak diberikan kekhususan untuk membentuk partai politik lokal namun dengan adanya ketentuan untuk memrioritaskan orang asli Papua dan kewajiban untuk meminta pertimbangan Majelis Rakyat Papua dalam rekrutmen politik oleh partai politik nasional lebih memberikan jaminan pengembangan sumber daya manusia di bidang politik bagi orang asli Papua pada khususnya dan penduduk Papua pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut keberadaan Pasal a quo sama sekali tidak menghalangi hak Pemohon untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat, akan tetapi justru memberikan kekhususan kepada orang asli Papua pada khususnya dan penduduk Papua pada umumnya untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasi, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui partai politik nasional.
[3.13.5] Bahwa untuk lebih memahami latar belakang pengaturan partai politik dalam UU 21/2001 tidak dapat dilepaskan dari proses pembahasannya yang berawal dari Rancangan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (RUU Otsus Papua) yang diinisiasi oleh DPR. Dalam RUU tersebut, salah satu aspek materi yang dibahas yakni aspek representasi politik, yakni bahwa penduduk Papua adalah sama seperti semua penduduk Indonesia yang telah dewasa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat membentuk partai politik. Bab VII tentang Partai Politik, Pasal 24 RUU Otsus Papua menyatakan sebagai berikut [vide Risalah Proses Pembahasan RUU Otsus Papua, hlm. 60]:
(1) Penduduk Provinsi Papua berhak membentuk Partai Politik;
(2) Tata cara pembentukan Partai Politik dan keikutsertaan dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(3) Rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai Politik di Provinsi Papua harus memprioritaskan masyarakat asli Papua;
(4) Partai Politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen partainya masing-masing;
Terhadap rancangan di atas, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum ke-2 dengan Pakar pada 28 Juli 2001, Ryaas Rasyid mengemukakan agar ketentuan dalam rancangan Pasal 24 ayat (1) RUU Otsus Papua perihal “penduduk Provinsi Papua berhak membentuk partai politik” diperjelas, apakah diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah atau melalui revisi undang-undang mengenai partai politik [vide Risalah Proses Pembahasan RUU Otsus Papua, hlm. 198]. Selengkapnya pendapat tersebut sebagai berikut:
… Pandangan saya pemilu lokal ini cita-cita saya dulu, dulu kan saya mengatakan bahwa pemilu tidak harus sama di tingkat daerah dengan nasional tapi ditolak oleh DPR yang lama. Nah, sekarang saya senang kalau diperjelas apakah pemilu di Irian mengikuti jadwal pemilu nasional atau punya jadwal sendiri. Apalagi di sini ada kewenangan keikutsertaan partai politik lokal berarti harus ada undang-undang lagi yang mengatur eksistensi partai politik lokal yang menyempal undang-undang partai yang ada sekarang yang mengharuskan sekian provinsi dari seluruh Indonesia bisa pemilu dan seterusnya. Jadi ini sebaiknya diperjelas ketentuan mengenai partai politik lokal, apakah diatur lebih lanjut dalam peraturan dasar atau peraturan pemerintah lebih lanjut atau revisi undang-undang mengenai partai politik kita dan juga mengenai jadwal pemilu di daerah provinsi Irian.
Terhadap pendapat pakar di atas, Paturungi Parawansa dari F-PG menanyakan plus minus partai politik lokal, sebagai berikut [vide Risalah Proses Pembahasan RUU Otsus Papua, hlm. 224]:
… juga mengenai kemungkinan adanya Partai Politik lokal di Provinsi Papua nanti, saya kira juga secara hati nurani menganggap bahwa partai politik lokal itu bagus saja diadakan walaupun di dalam RUU kita itu dalam undangundang itu tidak mengenalnya tetapi saya kira ke depan ini, mengapa tidak kita membangun suatu partai politik lokal di samping ada partai politik nasional yang menjadi pertanyaan saya itu menurut kajian Prof. Ryaas sepanjang melakukan comprehensive study dengan bacaan-bacaan maupun pengalamannya di lain-lain negara, apakah ada plus minus dari adanya partai lokal di suatu daerah katakanlah seperti Provinsi Irian Jaya.
Terhadap pertanyaan di atas, Ryaas Rasyid menyampaikan penjelasan sebagai berikut. [vide Risalah Proses Pembahasan RUU Otsus Papua, hlm. 251- 252]
… Kemudian mengenai Partai Politik Lokal, nah ini juga apa plus minusnya. Saya tidak ingin bertanya kepada kawan-kawan dari Irian ini, sebab Partai Politik Lokal itu akan membatasi proses kaderisasi mereka, lalu mereka akan terikat hanya pada isu-isu lokal, karier Politiknya juga tidak bisa berkembang, karena tidak mungkin masuk ke DPR misalnya saja, atau menjadi wakil ke MPR, itu sulit sekali. Karena persentasinya tentu akan terbatas sekali, dan saya pikir perlu dipikirkan kembali sejauh mana sih kita punya keperluan atas Politik Lokal, apakah saudara perlu punya nama? kalau soal program, kan itu bisa dimainkan oleh Partai-partai setempat dengan Program setempat begitu, jadi itu juga merupakan satu yang sangat penting, oleh karena saya khawatir Partai Politik Lokal itu tidak terlalu banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan Sumber Daya Manusia Irian, seandainya Partai Politik dunia Bapak masih di situ bahkan, bukan bikin Partai Lokal begitu, seandainya ada ya, soalnya ini Irian tidak bisa melihat dirinya ke dalam dia harus melihat keluar, Bapak sudah bilang bahwa di situ beberapa pasal itu mau berunding dengan luar negeri, kerja sama Luar negeri, perdagangan, ekonomi dan segala macam.
Mengapa itu direspon dengan Partai Politik Lokal, saya kira itu sesuatu yang tidak konsisten. Toh perjuangan untuk kepentingan lokal sudah ada Dewan Adat, sudah ada LSM-LSM, dan susah juga mendudukkannya dalam konteks nasional, apa perlunya begitu? Jadi saya kira ini bisa dipikirkan kembali karena menyangkut kaderisasi Partai dan juga persiapan Pemimpinpemimpin Irian di masa depan, dan kalau dia cuma kader Partai Lokal tidak mungkin dia dibayar untuk menjadi Menteri di Jakarta, bisa saja begitu, seluruh bisnis, seluruh kader ini hanya berkutat pada isu-isu lokal. Bagaimana dia bisa menjadi Duta Besar misalnya saja, kan ini kita masih mengharapkan begitu, dan terus terang saya masih konsen dengan itu, saya punya satu teori, orang Irian dengan orang Aceh itu mengapa kadangkadang mau berontak, kadang-kadang tidak puas, itu sebenarnya mereka tidak menikmati Indonesia, dan mereka tidak menikmati Indonesia seperti halnya lain-lain, sebagaimana orang Dayak, dia tidak merasa menjadi bagian Indonesia yang besar itu, berapa banyak orang Irian yang menjadi Pejabat di Jakarta, Depdagri tidak pernah ada, sampai hari ini selama sejarah, jadi staf ahli juga tidak, jadi dia itu mungkin satu dua orang, satu pun juga tidak ada sekarang malah, yang diatur seluruh Depdagri, Departemen Perdagangan, Departemen mana ada nggak orang Irian menjadi Pejabat di Sulawesi, di Sumatera Utara, tidak ada kan, orang Aceh juga sama, sehingga dia gampang sekali di provokasi atau tiba-tiba dia minta Indonesia kok saya belum menjadi bagian yang tidak menikmati begitu, paling ini dari orang Makassar, orang Batak, orang Padang kan menikmati semua, dimana-mana ada kan, jadi Indonesia itu menjadi penting sekali buat mereka, nah ini perlu kita pikirkan, kaderasasi Bapak itu, supaya lebar kemana-mana begitu dan ktemulah dengan pemikiran yang hanya Irian untuk Irian begitu, dan malah ini menjadi satu beban jangka panjang kalau menurut saya.
Pembahasan mengenai partai politik di Papua mengemuka kembali dalam Rapat Dengar Pendapat Umum ke-3 dengan Tim Asistensi Pemda Provinsi Irian Jaya pada 3 September 2001. Muhammad Musa’ad (Anggota Tim Asistensi) menyampaikan pembentukan partai politik merupakan salah satu kekhususan [vide Risalah Proses Pembahasan RUU Otsus Papua, hlm. 273]. Selengkapnya sebagai berikut:
… ada satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa di samping partai-partai politik yang telah ada, kita juga memberikan peluang untuk dibentuknya partai politik lokal, ini sesuatu yang baru. Tetapi kalau kita mengkaji Undang-Undang tentang Parpol dan kemudian kita mencoba untuk memprediksi ke depan dengan menggunakan sistem distrik maka kami yakin bahwa sebenarnya pembentukan parpol bukan merupakan sesuatu yang luar biasa. Ketiga kita menggunakan sistem distrik misalnya, maka setiap orang bisa mencalonkan diri menjadi anggota Dewan untuk dipilih oleh masyarakat. Apa lagi ada sekelompok orang yang membentuk parpol. Ini adalah sesuatu yang memang berbeda dengan undang-undang yang telah ada. Tetapi saya mengajak kita sekalian untuk mencoba menyampaikan tali sejak awal menangkap suasana kebatinan, dan ini adalah kekhususan-kekhususan yang coba kita ke depankan. Kalau kemudian kita tidak bisa menampilkan kekhususan, maka saya yakini bersama bahwa kita tidak bisa menyelesaikan problem yang ada di rakyat Papua.
Sebelum rapat dengan Tim Asistensi berakhir, Ferry Mursyidan Baldan dari F-PG menyampaikan ada beberapa hal yang perlu didalami lagi dengan pendampingan Tim Asistensi, di antaranya sebagai berikut [vide Risalah Proses Pembahasan RUU Otsus Papua, hlm. 296]:
… itu juga kita perlu memerlukan satu argumen pendalaman kemudian urgensi partai politik lokal dengan kewenangan-kewenangannya dalam kaitan dan hubungannya dengan Partai Politik secara nasional…
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Asistensi Pemda Provinsi Irian Jaya berlanjut keesokan harinya pada 4 September 2001. Dalam RDPU ini, kembali Muhammad Musa’ad (Anggota Tim Asistensi) menyampaikan bahwa pembentukan partai politik di Papua tidak berarti tidak mengakui partai politik nasional [vide Risalah Proses Pembahasan RUU Otsus Papua, hlm. 332]. Selengkapnya sebagai berikut:
Persoalan yang kemudian muncul, apakah dengan pembentukan partai politik lokal, kemudian kita tidak mengakui partai politik nasional, jawabannya adalah tidak. Partai politik lokal adalah merupakan salah satu wujud dari partisipasi politik dan mempunyai kedudukan yang sama dengan partai politik nasional di lingkup provinsi Papua. Partai politik lokal bisa saja melakukan afiliasi dengan partai politik nasional yang platform-nya sama, sehingga aspirasi lokal ini ketika diangkat pada tingkat nasional itu bisa terakomodir di partai-partai tertentu yang dianggap mempunyai platform yang sama. Oleh karena itu maka dalam konteks ini sebenarnya tidak ada persoalan, tidak ada perbedaan antara partai nasional dan partai produk lokal.
Pembahasan RUU Otsus Papua selanjutnya dibawa dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus). Dalam Rapat Kerja Pansus dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah pada 10 Oktober 2001, pembentukan partai politik di Papua ikut disinggung. Dalam Rapat Kerja tersebut, Marthina Meheu Wally dari FPG meminta hak diberikan kepada penduduk adalah membentuk partai nasional di daerah, bukan partai lokal [vide Risalah Proses Pembahasan RUU Otsus Papua hlm. 704]. Berikut ini selengkapnya:
Dan hal lain yang ingin saya sampaikan di sini awalnya kita meminta partai lokal tetap di sini dengan jelas dijelaskan bahwa penduduk Provinsi Papua berhak membentuk partai politik bukan partai lokal. Tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini kan berbicara kesempatan pembangunan bangsa kita bukan bangsa orang lain dan seterusnya ke bawah. Saya tidak perlu menjelaskan karena tadi Pak Alex sudah menjelaskan mengapa demikian dan kondisi nil di daerah memang demikian. Mereka memanfaatkan keluguan dan kelabilan masyarakat banyak orang memanfaatkan sebaik mungkin.
Sedangkan Partai Demokrasi Kasih Bangsa di Jayapura memang pemilihnya orang awam Irian tetapi yang duduk di sana bukan orang Irian, itu persoalan. Mengapa? Karena mereka memanfaatkan keluguan orang Irian sebaik mungkin. Oleh sebab itu kami meminta dalam rancangan ini bahwa penduduk Provinsi kami berhak membentuk partai nasional di daerah. Itu bukan partai lokal itu partai nasional, itu persoalan pertama. Mengapa persoalan ini timbul teman-teman sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Oleh sebab itu kami minta kalau bisa ini ditanggapi serius, beri tempat yang layak bagi mereka untuk ikut berkiprah di dunia politik, terima kasih.
Sementara itu, Anthonius Rahail dari F-KKI memberi catatan dengan tidak disebutkannya partai lokal dalam RUU Otsus sebagai berikut [vide Risalah Proses Pembahasan RUU Otsus Papua, hlm. 705):
Dengan demikian kami tidak menyebutkan partai politik lokal di dalam RUU ini. Tetapi sepanjang kebutuhan masyarakat seperti tadi disampaikan oleh teman-teman, kami mengharapkan sekali tanggapan positif dari Pemerintah agar di dalam revisi undang-undang politik di depan sudah ada pemikiran mengenai partai politik lokal. Ini juga berkenaan dengan HAM dan demokrasi yang sekarang menjadi tren daripada dunia, tidak ada salahnya kalau lebih awal kita merespon ini. Sehingga ke depan kita tetap berada dalam suasana yang kompetitif ketika kita berbicara pengembangan HAM dan demokrasi yang memang melekat di dalam kehidupan partai politik sebagaimana tadi disampaikan oleh teman-teman.
Berdasarkan risalah pembahasan RUU Otsus Papua tersebut di atas, istilah “partai politik lokal” sebagai pemaknaan dari frasa “partai politik” dalam RUU a quo memang benar pernah muncul tetapi pendapat tersebut dikemukakan oleh salah seorang anggota Tim Asistensi RUU Otsus Papua. Apabila ditelusuri lebih jauh, yang bersangkutan konsisten menyebut istilah “partai politik lokal” selama proses pembahasan. Namun demikian, apabila dibaca secara saksama pendapat yang dikemukakan sejumlah anggota DPR yang tergabung dalam Pansus RUU Otsus Papua, frasa “partai politik” dimaksud bukanlah partai politik dalam pengertian “partai politik lokal”. Misalnya pendapat Marthina Meheu Wally dari F-PG secara eksplisit menyatakan “meminta dalam rancangan RUU Otsus Papua agar memberi hak kepada penduduk provinsi Papua membentuk partai politik nasional daerah”. Dengan demikian, yang dimaksudkan Marthina Meheu Wally bukanlah pembentukan partai politik lokal. Begitu pula Anthonius Rahail dari F-KKI secara tegas menyatakan dalam RUU Otsus Papua partainya tidak menyebut frasa “partai politik” sebagai partai politik lokal. Oleh karena itu, Anthonius Rahail menambahkan pula, agar gagasan “partai politik” dalam RUU Otsus Papua dimaksud ditampung dalam revisi undang-undang partai politik.
Akhirnya, setelah melewati serangkaian tahapan, hasil pembahasan Pansus RUU Otsus Papua dilaporkan kepada rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan atas RUU Otsus Papua pada 22 Oktober 2001. Pimpinan Pansus RUU Otsus Papua melaporkan hasil pembahasan RUU Otsus Papua, pendapat akhir fraksi-fraksi, dan sambutan Pemerintah terhadap pengambilan keputusan atas RUU Otsus Papua, disetujui RUU Otsus Papua menjadi Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Terkait pengaturan partai politik di Provinsi Papua diatur dalam Bab VII Partai Politik Pasal 28 menyatakan sebagai berikut:
(1) Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik;
(2) Tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(3) Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua;
(4) Partai Politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen partainya masing-masing.
Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, terdapat pergeseran substantif pola perumusan norma dari “Penduduk Provinsi Papua berhak membentuk partai politik” menjadi “Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik”. Secara normatif, perubahan kata “berhak” menjadi kata “dapat” mengakibatkan pola perumusan norma dimaksud bergeser dari sesuatu yang dekat dengan sifat imperatif menjadi bersifat fakultatif. Perubahan pola perumusan norma tersebut tetap mempertahankan konstruksi norma Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan “tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dalam batas penalaran yang wajar, frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 28 ayat (2) a quo tidaklah menggambarkan dan menunjukkan karakter sebagai sebuah partai politik lokal. Dengan demikian, pengaturan partai politik di Papua sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 UU 21/2001 bukanlah dimaksudkan sebagai partai politik lokal. Sebab, pengaturan partai politik dalam UU 21/2001 tidak secara tegas dikatakan dan sekaligus dimaknai sebagai partai politik lokal. Bahkan, bilamana hendak dibandingkan dengan UU 11/2006, keberadaan partai politik lokal disebut secara eksplisit dalam Ketentuan Pasal 1 angka 14 UU 11/2006. Tidak hanya penyebutan tersebut, UU 11/2006 pun menguraikan secara terperinci ihwal partai politik lokal dalam satu bab khusus, yaitu Bab XI Pasal 75 sampai dengan Pasal 95 UU 11/2006, yang mengatur mulai dari Pembentukan; Asas, Tujuan, dan Fungsi; Hak dan Kewajiban; Larangan; Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota; Keuangan; Sanksi; Persyaratan Mengikuti Pemilu Anggota DPRA/DPRK, Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan Pengawasan terhadap partai politik lokal. Artinya, jikalau pembentuk undang-undang bermaksud frasa “partai politik” dalam UU 21/2001 sebagai partai politik lokal, maka pengaturannya akan dilakukan secara terperinci berkenaan dengan segala sesuatu yang terkait dengan partai politik lokal. Selain itu, sebagaimana diuraikan pada Sub-paragraf [3.13.3] di atas, partai politik lokal memang tidak termasuk sebagai bentuk kekhususan yang diberikan UU 21/2001 dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Papua.
[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa frasa “partai politik” dalam Pasal 28 UU 21/2001 adalah partai politik lokal. Namun, dalam posisi sebagai salah satu daerah yang diberi status otonomi khusus, dalam hal apabila terdapat kesempatan untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang partai politik pada masa mendatang, pembentuk undang-undang dapat saja memberikan pengaturan khusus pengelolaan partai politik di Papua yang memungkinkan warga negara yang merupakan penduduk Papua memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat mengelola partai politik nasional yang berada di Papua. Bahkan, sebagai bagian dari demokratisasi partai politik, pengaturan khusus dimaksud dapat menjadi model percontohan desentralisasi pengelolaan partai politik nasional di daerah. Dalam batas penalaran yang wajar, kesempatan lebih luas untuk terlibat mengelola partai politik akan memberikan ruang lebih luas kepada warga negara penduduk Papua untuk mengisi jabatan-jabatan politik yang merupakan hasil kontestasi politik yang melibatkan partai politik. Namun demikian, jika pembentukan partai politik lokal akan dijadikan sebagai bagian dari kekhususan Papua, pembentuk undang-undang dapat melakukan dengan cara merevisi UU 21/2001 sepanjang penentuannya diberikan sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan nyata Papua serta tetap dimaksudkan sebagai bagian dari menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat frasa “Partai Politik” pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU 21/2001 adalah konstitusional secara bersyarat sepanjang dimaknai sebagai “Partai Politik Lokal” sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.
Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430