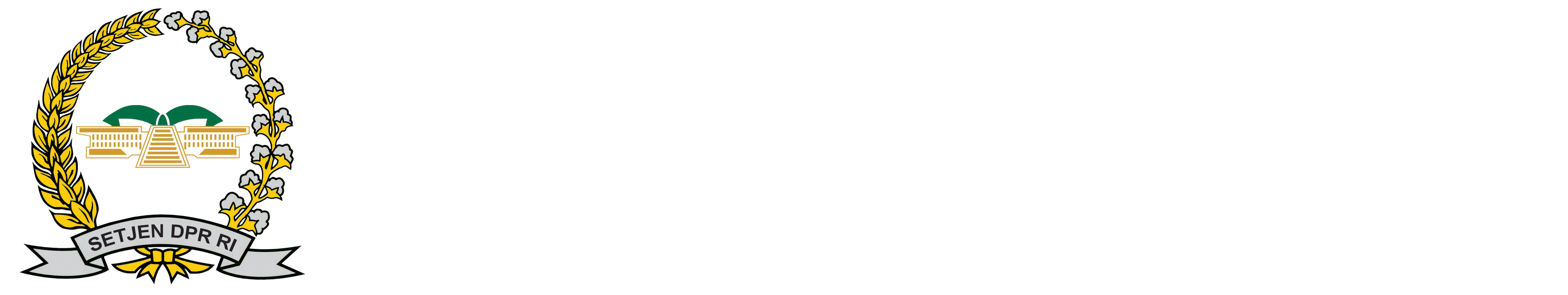
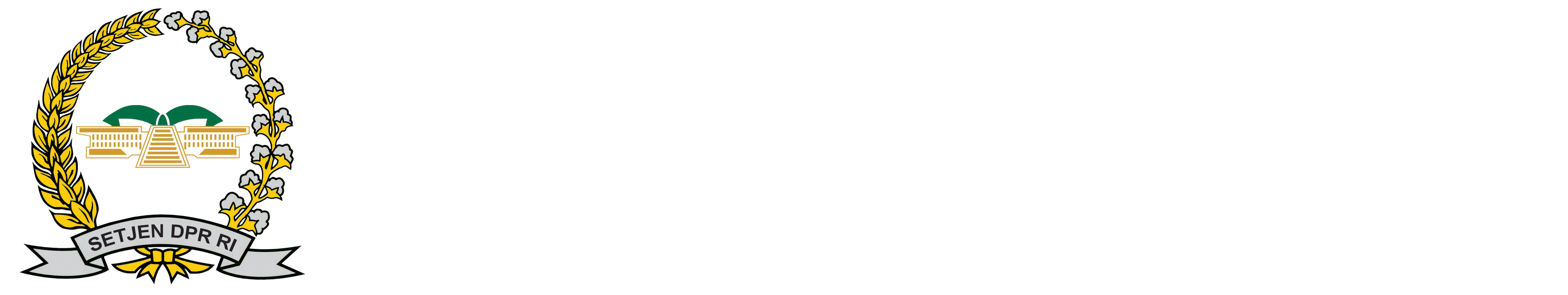

Wahyu Nugroho, S.HI., M.H., Deri Hafizh S.H., M.M., M.H., dan Rudi Heryandi Nasution, S.H.
Pasal 16 UU 18/2003
Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28G ayat (2) UUD Tahun 1945
perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI
Bahwa terhadap pengujian Pasal 16 UU 18/2003 terhadap frasa “Itikad Baik” dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
[3.11.1] Bahwa meskipun para Pemohon mendalilkan alasan permohonan Pemohon dan dasar pengujiannya dalam permohonan a quo berbeda dengan perkara Nomor 26/PUU-XI/2013, namun sesungguhnya substansi permohonan para Pemohon baik semangat maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan adalah sama dengan perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018, dan terhadap hal tersebut Mahkamah telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018, bertanggal 27 Februari 2019, yaitu bahwa menurut Pemohon, advokat dalam melaksanakan tugasnya baik dalam persidangan maupun di luar persidangan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana sebelum terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh DKOA. Terhadap substansi permohonan demikian Mahkamah telah menjatuhkan putusannya yang diucapkan sebelumnya dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon dalam perkara dimaksud dengan pertimbangan antara lain:
[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan maksud yang terkandung dalam pengertian “iktikad baik”. Secara gramatikal, menurut Black’s Law Dictionary, “In or with good faith, honestly, openly and sincerely, without deceit or fraud truly, actually, without simulation or pretense”. Sementara itu, secara doktrinal iktikad baik merupakan perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, akal-akalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain. Apabila diletakkan dalam konteks hukum perjanjian, misalnya iktikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjianya maupun tidak merugikan kepentingan umum. Artinya, iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan kepatutan dan kepantasan. Dengan demikian, iktikad baik adalah pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan sehingga orang lebih banyak merumuskannya melalui peristiwa- peristiwa atau kasus-kasus konkret yang diajukan ke pengadilan. Adapun dalam konteks hukum pidana, “iktikad baik” secara universal bukanlah suatu unsur delik yang dikenal dalam tindak pidana.
[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan hak imunitas Advokat yang diatur dalam Pasal 16 UU 18/2003 a quo tidak memberikan jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil, perlakuan diskrimintatif, tidak melindungi hak pribadi, kehormatan dan martabat bagi para Pemohon. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
[3.13.1] Bahwa Advokat merupakan salah satu bagian dari penegak hukum yang memiliki tugas memberikan bantuan hukum kepada masyarakat (klien) yang mengalami masalah hukum, sehingga dengan demikian keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Secara prinsipil, Advokat adalah officium nobile artinya sebuah profesi yang terhormat, yakni seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dapat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan klien. Dalam kerangka pembelaan hukum, Advokat diberikan keistimewaan berupa hak imunitas oleh undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UU 18/2003 yang menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Bahkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, bertanggal 14 Mei 2014, imunitas tersebut berlaku baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sehingga, terhadap Pasal 16 UU 18/2003 sejak tanggal 14 Mei 2014 harus ditafsirkan sesuai dengan putusan Mahkamah dimaksud. Hak imunitas Advokat yang diatur dalam Pasal 16 UU 18/2003 merupakan ketentuan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai kebebasan Advokat yang diatur sebelumnya dalam Pasal 15 UU 18/2003, yang menyatakan bahwa “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU- XI/2013, tanggal 14 Mei 2014, menyatakan “Mahkamah perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 harus dimaknai advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”. Pertimbangan Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 sangat jelas menekankan bahwa Advokat dijamin serta dilindungi kebebasannya dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya diperluas tidak hanya kebebasan itu berlaku di dalam persidangan tetapi termasuk pula di luar persidangan. Bila menggunakan penafsiran sistematis dan mengacu kepada Pasal 6 dan Pasal 15 UU 18/2003 maka jika yang menjadi batasan iktikad baik Advokat dalam menjalankan profesinya adalah tidak boleh bertentangan dengan kode etik, peraturan perundang-undangan, sumpah janji Advokat, serta nilai-nilai kelayakan dan ketatutan yang ada di masyarakat. Apabila tindakan Advokat bertentangan dengan kode etik, peraturan perundang-undangan, sumpah atau janji Advokat serta nilai-nilai kelayakan dan kepatutan, maka Advokat tersebut telah tidak beriktikad baik.
[3.13.2] Bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.13.1] di atas, hak imunitas Advokat yang dijamin dan dilindungi dalam UU 18/2003 tidak serta-merta membuat Advokat menjadi kebal terhadap hukum. Karena hak imunitas tersebut digantungkan kepada apakah profesinya dilakukan berdasarkan iktikad baik atau tidak. Dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 dinyatakan, “Yang dimaksud dengan iktikad baik adalah menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya”. Maka dengan demikian pengertian iktikad baik yang diberikan dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 mensyaratkan dalam membela kepentingan kliennya pun Advokat harus tetap berdasarkan aturan hukum. Lebih lanjut, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 7/PUU-XVI/2018 dinyatakan, “Kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada “kepentingan pembelaan Klien” melainkan pada “itikad baik”. Artinya, secara a contrario, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur “itikad baik” dimaksud tidak terpenuhi”. Maka dengan demikian kebebasan atau hak imunitas profesi Advokat saat melaksanakan tugas pembelaan hukum kepada kliennya harus didasarkan kepada itikad baik yakni berpegang pada Kode Etik dan Peraturan Perundang-undangan. Dengan kata lain kebebasan Advokat ketika melaksanakan tugas profesinya tersebut diatur pada ranah etik dan ranah hukum sehingga seorang Advokat pun harus tunduk pada etika profesi dan mematuhi hukum.
[3.13.3] Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon yang beranggapan hanya DKOA yang berhak menilai iktikad baik dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Advokat, Mahkamah berpendapat, Advokat dalam menjalankan tugas profesinya harus mematuhi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persoalan selanjutnya yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah iktikad baik yang dimaksud oleh para Pemohon apakah iktikad baik tersebut termasuk dalam hal pelanggaran kode etik atau perbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Kode etik merupakan prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi yang disusun secara sistematis. Kode Etik Advokat pada dasarnya merupakan sebuah etika atau norma-norma dasar yang menjadi acuan bagi seorang Advokat untuk bertindak dalam menjalankan tugas dalam kesehariannya. Sehingga iktikad baik yang dimaksud dalam kode etik advokat adalah berkaitan dengan niat baik yang dilakukan oleh Advokat ketika melakukan tugas profesinya. Sebagai contoh, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 UU 18/2003 dan Pasal 4 huruf h Kode Etik Profesi Advokat dimana seorang Advokat tidak boleh menggunakan rahasia kliennya untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan pihak ketiga, dan jika diketahui terdapat Advokat yang melanggar kode etik Advokat tersebut, maka berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UU 18/2003 merupakan kewenangan DKOA untuk melakukan pengawasan, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (5) UU 18/2003 DKOA berhak memeriksa serta mengadili pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara DKOA. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 26 ayat (6) UU 18/2003 dinyatakan, “Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana”. Dengan demikian telah jelas bahwa kewenangan DKOA hanya berkait dengan nilai-nilai moral yang melekat pada profesi Advokat (Kode Etik Profesi Advokat), sehingga untuk menilai iktikad baik yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Advokat tentunya bukan lagi menjadi wilayah kewenangan DKOA tetapi menjadi kewenangan penegak hukum dalam kasus konkret yang dihadapi oleh seorang advokat, baik perbuatan pidana maupun perdata. Jika ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 diubah seperti rumusan petitum permohonan para Pemohon maka akan terjadi pertentangan dengan Pasal 26 UU 18/2003.
[3.13.4] Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan proses hukum bagi Advokat yang diduga melakukan pelanggaran pidana atau perbuatan melawan hukum atau setidaknya akan diperiksa oleh Kepolisian harus menunggu hasil pemeriksaan DKOA yang menurut para Pemohon terdapat perlakuan berbeda dengan penegak hukum lainnya. Berkaitan dengan dalil para Pemohon terkait hal tersebut, Mahkamah perlu membandingkan dengan profesi Jaksa ketika diduga melakukan tindak pelanggaran pidana maupun perbuatan melawan hukum perdata. Jaksa merupakan komponen kekuasaan eksekutif di bidang penegak hukum dan dalam menjalankan profesinya memiliki kode etik profesi yang dalam institusi Kejaksaan dikenal dengan Kode Perilaku Jaksa (vide Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/ 11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, selanjutnya disebut Kode Perilaku Jaksa). Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai UU Kejaksaan) dinyatakan:
(1) Apabila terdapat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan terhadap seorang jaksa, dengan sendirinya yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.
(2) Dalam hal jaksa dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, jaksa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.
Pasal 15 UU Kejaksaan tersebut telah menjelaskan bahwa ketika seorang Jaksa diduga telah melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum secara perdata maka dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung. Dalam hal ini bukanlah berarti proses hukum terhadap Jaksa tersebut terhenti dan menunggu izin dari Jaksa Agung sebagaimana disebutkan dalam permohonan para Pemohon. Lebih lanjut Pasal 12 Kode Perilaku Jaksa menyatakan, “Tindakan administratif tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukuman disiplin berdasarkan peraturan disiplin pegawai negeri sipil apabila atas perbuatan tersebut terdapat ketentuan yang dilanggar”, yang artinya proses hukum dapat berjalan secara bersamaan dengan proses pemeriksaan etik di Kejaksaan. Hal tersebut dikarenakan pelanggaran etik dengan pelanggaran pidana atau perdata dari seorang Jaksa merupakan dua hal yang berbeda untuk dinilai dan tidak harus menunggu salah satu proses pemeriksaan dari keduanya selesai lebih dulu.
Menurut Mahkamah, dalam konteks demikian, dalam posisi sebagai sesama penegak hukum, maka penanganan pelanggaran kode etik yang berlaku terhadap Jaksa seharusnya tidak berbeda dengan penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat. Artinya, jika seorang Advokat dalam menjalankan profesinya diduga melakukan pelanggaran pidana atau perbuatan melawan hukum maka proses penegakan etik yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh DKOA tidak menghentikan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum karena pemeriksaan yang dilakukan oleh DKOA tersebut merupakan proses penegakan etik yang berkait dengan pelaksanaan profesi. Sedangkan proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum adalah berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana yang diduga dilakukan oleh seorang advokat yang tetap harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula dalam hal adanya dugaan perbuatan advokat yang merugikan secara keperdataan pihak lain termasuk dalam hal ini prinsipal (klien), maka penilaian iktikad baik menjadi kewenangan hakim perdata yang mengadili perkara yang bersangkutan.
[3.14] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya dasar permohonan para Pemohon tidak relevan atau tidak mempunyai landasan argumentasi yang dapat dibenarkan oleh Mahkamah, hal itu tidak menghilangkan kewenangan DKOA untuk melakukan pemeriksaan anggotanya (advokat) yang diduga telah melakukan tindak pidana maupun perbuatan melawan hukum lainnya yang hasilnya dapat dijadikan bahan pembelaan di dalam proses hukum yang dihadapi oleh advokat yang bersangkutan, sepanjang hal tersebut tidak bersifat mengikat bagi penegak hukum yang menangani perkara yang berkaitan dengan advokat tersebut.
[3.11.2] Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 52/PUU-XVI/2018 di atas yang telah diucapkan sebelumnya, dan oleh karena isu konstitusional terhadap norma pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon beserta argumentasi atau dalil yang dijadikan dasar permohonan para Pemohon secara substansial adalah sama, maka pertimbangan hukum dalam perkara tersebut berlaku pula terhadap pertimbangan hukum dalam perkara a quo.
[3.11.3] Bahwa mengenai dasar pengujian yang berbeda dengan perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018, yaitu Pasal 28G ayat (2) UUD 1945, meskipun secara formal dijadikan salah satu dasar pengujian oleh para Pemohon yang kemudian membedakan dengan permohonan-permohonan sebelumnya, namun substansi argumentasi para Pemohon tidak ada kaitan sama sekali dengan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 dimaksud. Menurut Mahkamah penambahan dasar pengujian yang diajukan oleh para Pemohon hanya dimaksudkan semata-mata untuk memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005, dengan tujuan agar permohonan a quo dapat diajukan kembali.
Berdasarkan pertimbangan pada Paragraf [3.11.2] dan Paragraf [3.11.3] di atas, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018 mutatis mutandis berlaku terhadap pokok permohonan para Pemohon a quo sehingga pokok permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715467, 021-5715855, Fax : 021-5715430